Bissmillah..
Hmmm dimulai darimana yaa?
Baiklah pertama-tama ingin saya ucapkan adalah:
"Alhamdulillah.."
malam ini benar-benar suatu kejadian yang tak terduga, saya cukup bersyukur.
Allah telah merencanakannya, Ia menurunkan hujan yang deras menunda si penyejuk hati menunda untuk pulang ke rumah. Di saat itulah saya beranikan untuk menyapanya, sedikit canggung.. Karena kalimat pertanyaan yang saya ucapkan tanpa sadar adalah:
"Hmm... sudah menikah yaa?"
waow.. Apakah anda terkejut? Sama kalo begitu, saya juga..
Dari senyumnya yang berwibawa tiba-tiba terukir tawa kecil
"Hehe, beluuummm.. Kenapa, apa terlihat tua yaa?"
ehhh.. Saya jawab apa kalo begini?
"Wah maaf, habis mbak terlihat lebih dewasa."
Saya malu. Malu, sodara sodara...
"Memang umurnys berapa?"
Hmmm..
"Kelahiran 91, kalo mbak?"
dan tarnyata..
"89. Beda dua tahun yah.."
Astagfirullah, Kami hanya berbeda dua tahun. Tapi dia terlihat dewasa dan bertanggung jawab.
Singkat dari obrolan kami, dapat saya simpulkan titik perbedaaan kami. Dia berani berdakwah kecil menjadi guru mengaji adik kecilku, juga bekerja di sebuah klinik herbal serta memiliki segudang kegiatan positif. Sedangkan saya?? Tak perlu kujelaskan saya ini seperti apa.. Tapi Ya Allah, saya iri padanya, ya Allah, juuga malu di hadapanmu, saya hanya yang paling kecil.
Ya Allah, berikanlah saya kekuatan untuk menjadi lebih baik lagi..
Untuk engkau ukhti, yang namanya berarti 'jembatan' semoga engkau kelak menjadi jembatan hidup untuk mereka yang ingin menyebrang ke arah kebaikan.. Aamin..
SEmoga ketika kita berjumpa kembali, Saya sudah memiliki jembatan yang kokoh dan dapat dipijaki tanpa ada ragu akan terjatuh...
semoga manfaat
Ahad bersama malam
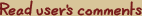
PERCOBAAN 2 TEKNIK STERILISASI DAN PEMBUATAN MEDIA
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Tujuan Percobaan
Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengenal beberapa cara sterilisasi, memperoleh alat dan media yang steril, dan mengetahui macam-macam media dan cara pembuatannya
1.2 Latar Belakang
Sterilisasi adalah proses atau kerja untuk membebaskan suatu bahan seperti medium pertumbuhan mikroba ataupun peralatan laboratorium dari semua bentuk kehidupan. Sterilisasi merupakan suatu proses untuk membunuh semua jasad renik yang ada, sehingga jika ditumbuhkan di dalam suatu medium tidak ada lagi jasad renik yang dapat berkembang biak. Sterilisasi harus bisa membunuh jasad renikyang paling tahan panas seperti spora bakteri (Fardiaz, 1992).
Media adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat hara (nutrient) yang berguna untuk membiakkan mikroba. Dengan menggunakan bermacam-macam media dapat dilakukan isolasi, perbanyakan, pengujian sifat-sifat fisiologis dan perhitungan sejumlah mikroba. Supaya mikroba dapat tumbuh baik dalam suatu media, maka medium tersebut harus memenuhi syarat-syarat
(Sutedjo, 1991).
Hampir semua tindakan yang dilakukan dalam diagnosa mikrobiologis, sterilisasi sangat diutamakan baik alat-alat yang siap pakai maupun medianya. Suatu alat atau bahan dikatakan steril apabila alat atau bahan tersebut bebas dari mikroba baik dalam bentuk vegetatif maupun spora. Oleh karena itu, bagi seorang pemula di bidang mikrobiologi sangat perlu mengenal teknik sterilisasi, pembuatan media serta teknik penanaman, hal ini semua merupakan dasar-dasar kerja dalam laboratorium mikrobiologi.
BAB II DASAR TEORI
Mikroorganisme dapat ditumbuhkan dan dikembangkan pada suatu substrat yang disebut medium. Medium yang digunakan untuk menumbuhkan dan mengembangbiakkan mikroorganisme tersebut harus sesuai susunanya dengan kebutuhan jenis-jenis mikroorganisme yang bersangkutan. Beberapa mikroorganisme dapat hidup baik pada medium yang sangat sederhana yang hanya mengandung garam anargonik ditambah sumber karbon organik seperti gula. Sedangkan mikroorganime lainnya memerlukan suatu medium yang sangat kompleks yaitu berupa medium ditambahkan darah atau bahan-bahan kompleks lainnya (Volk dan Wheeler, 1993).
Sterilisasi berarti proses pemusnahan bakteri dengan cara membunuh mikroorganisme. Dalam kegiatan penelitian mikroba, digunakan alat dan medium yang steril, maka sterilisasi ini adalah usaha untuk membebaskan alat atau bahan-bahan dari segala macam kehidupan atau kontaminasi oleh mikroba. Sterilisasi ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
1. Pemanasan, meliputi:
a. Sterilisasi dengan pemijaran (pembakaran alat-alat di atas lampu spiritus sampai pijar).
b. Sterilisasi dengan udara panas (kering). Temperatur yang digunakan 170°C – 180°C selama 2 jam.
c. Sterilisasi dengan uap air panas. Digunakan untuk cairan dengan suhu 100°C.
d. Sterilisasi dengan uap panas bertekanan, menggunakan otoklaf dengan suhu 121°C selama 12 – 30 menit.
2. Penyaringan
Dilakukan terhadap bahan cair yang sangat peka terhadap pemanasan (misal: serum darah, toksin, larutan garam fisiologis) dan tidak dapat disterilkan dengan pemanasan tinggi. Untuk itu digunakan filter bakteri, misalnya Berkeled filter, Chamberland filter.
3. Sterilisasi Bahan Makanan
Sterilisasi bahan makanan dapat dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam uap air panas selama 1 jam dengan suhu 100°C diulang selama tiga kali. Cara lain adalah dapat disterilkan dengan menggunakan autoklaf
(Pustekkom, 2005).
Faktor–faktor yang mempengaruhi sterilisasi pemanasan:
1. jenis pemanasan, kering atau basah
2. suhu dan waktu
3. jumlah organisme yang ada
4. apakah organisme tersebut memiliki kemampuan untuk membuat spora
5. jenis bahan yang mengandung organisme yang harus dibunuh
(Gupte, 1990):
Autoklaf digunakan sebagai alat sterilisasi uap dengan tekanan tinggi. Penggunaan autoklaf untuk sterilisasi, tutupnya jangan diletakkan sembarangan dan dibuka-buka karena isi botol atau tempat medium akan meluap dan hanya boleh dibuka ketika manometer menunjukkan angka 0 serta dilakukan pendinginan sedikit demi sedikit. Medium yang mengandung vitamin, gelatin atau gula, maka setelah sterilisasi medium harus segera didinginkan. Cara ini untuk menghindari zat tersebut terurai. Medium dapat langsung disimpan di lemasi es jika medium sudah dapat dipastikan steril (Dwidjoseputro, 1994).
Komposisi Nutrien Agar per liter :
- Agar 15,0 gram
- Peptone 5,0 gram
- NaCl 5,0 gram
- Yeast Extract 2,0 gram
- Beef Extract 1,0 gram
pH 7,4 ± 0,2 pada 25oC
(Atlas, 2005).
Media berfungsi untuk menumbuhkan mikroba, isolasi, memperbanyak jumlah, menguji sifat-sifat fisiologi dan perhitungan jumlah mikroba, dimana dalam proses pembuatannya harus disterilisasi dan menerapkan metode aseptis untuk menghindari kontaminasi pada media. Nutrien agar adalah medium umum untuk uji air dan produk dairy. NA juga digunakan untuk pertumbuhan mayoritas dari mikroorganisme yang tidak selektif, dalam artian mikroorganisme heterotrof. Media ini merupakan media sederhana yang dibuat dari ekstrak beef, pepton, dan agar. NA merupakan salah satu media yang umum digunakan dalam prosedur bakteriologi seperti uji biasa dari air, sewage, produk pangan, untuk membawa stok kultur, untuk pertumbuhan sampel pada uji bakteri, dan untuk mengisolasi organisme dalam kultur murni dengan caradisterilisasi dengan autoklaf pada 121°C selama 15 menit (Fathir, 2009).
Media dibedakan menjadi:
1. Media umum, yaitu media yang dapat dipergunakan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan satu atau lebih kelompok mikroba secara umum.
2. Media pengaya, yaitu dipergunakan dengan maksud “memberikan kesempatan” terhadap suatu jenis atau kelompok mikroba untuk tumbuh menjadi cepat.
3. Media selektif, yaitu media yang hanya dapat ditumbuhi oleh satu atau lebih jenis mikroba tertentu tetapi akan menghambat atau mematikan untuk jenis-jenis lainnya.
4. Media diferensiasi, yaitu media yang dipergunakan untuk pengujian senyawa atau benda tertentu dengan bantuan mikroba.
5. Media penguji, yaitu media yang dipergunakan untuk pengujian senyawa atau benda tertentu dengan bantuan mikroba.
6. Media enumerasi, yaitu media yang dipergunakan untuk menghitung jumlah mikroba pada suatu bahan.
(Suriawiria, 2005).
Garis besar pembuatan media yang tersusun atas beberapa bahan adalah sebagai berikut:
a. Mencampur bahan – bahan, dilarutkan dalam air suling dan dipanaskan dalam pemanas air supaya larutannya homogen.
b. Menyaring dengan kertas saring, kain, atau kapas. Untuk media agar atau gelatin, penyaringan harus dilakukan dalam keadaan panas.
c. Menentukan dan mengatur pH.
d. Memasukkan media ke dalam tempat tertentu. Sebelum disterilkan, media dimasukkan ke dalam erlenmeyer atau wadah lain yang bersih, kemudian ditutup kapas atau kertas sampul (kertas perkamen) supaya tidak basah sewaktu disterilkan.
e. Sterilisasi umumnya dilakukan dengan udara panas dalam autoclave pada suhu 1210 C selama 15- 30 menit
(Sutedjo, 1991).
PH merupakan faktor yang sangat mempengaruhi suatu keberhasilan dalam pembuatan medium sehingga kondisi pH yang terlalu basa atau terlalu asam tidak cocok untuk dijadikan medium mikroba karena mikroba tidak dapat hidup pada kondisi tersebut. Medium didiamkan atau disimpan selama 2 x 24 jam untuk menyakinkan bahwa medium masih steril, karena selain pH sebagai penentu tumbuhnya mikroba, alat dan medium yang steril juga menentukan (Dwidjoseputro, 1994).
BAB III METODOLOGI PERCOBAAN
3.1 Alat
Alat-alat yang digunakan pada percobaan ini adalah Erlenmeyer, pipet volume, autoklaf, gelas ukur, neraca analitik, magnetik stirer, hot plate, dan tabung reaksi.
3.2 Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah media Nutrien Agar, Malt Extract Agar, Potato Destroxe Agar, dan akuades.
3.3 Prosedur Kerja
a. Pembuatan Media Nutrien Agar (NA)
1. Dibuat media NA (20 gram/L) dengan dicampurkan pepton sebanyak 5 gram, meat extract sebanyak 3 gram, dan Agar sebanyak 12 gram ke dalam erlenmeyer.
2. Ditambahkan 50 mL akuades. hingga dihasilkan NA sebanyak sebanyak 1 gram.
3. Dipanaskan di atas hot plate hingga mendidih sambil diaduk dengan stirer magnetik sampai homogen, lalu dibiarkan beberapa saat.
4. Dimasukkan ke dalam 3 tabung reaksi masing-masing sebanyak 4 mL
5. Disumbat Mulut tabung Reaksi menggunakan kapas
6. Dimasukkan dalam autoklaf untuk disterilkan beserta alat-alat yang akan digunakan pada suhu 121oC dan tekanan 15 psi.
b. Pembuatan Potato Destroxe Agar (PDA)
1. Dibuat media PDA (39 gram/L) dengan dicampurkan potato sebanyak 4 gram, glukosa sebanyak 20 gram, dan Agar sebanyak 15 gram ke dalam erlenmeyer.
2. Ditambahkan 50 mL akuades. Hingga dihasilkan PDA sebanyak sebanyak 1,95 gram.
3. Dipanaskan di atas hot plate hingga mendidih sambil diaduk dengan stirer magnetik sampai homogen, lalu dibiarkan beberapa saat.
4. Dimasukkan ke dalam 3 tabung reaksi masing-masing sebanyak 4 mL.
5. Disumbat Mulut tabung Reaksi menggunakan kapas
6. Dimasukkan dalam autoklaf untuk disterilkan beserta alat-alat yang akan digunakan pada suhu 121oC dan tekanan 15 psi.
c. Pembuatan Media Malt Extract Agar (MEA)
1. Dibuat media MEA (48 gram/L) dengan dicampurkan pepton sebanyak 3 gram, meat extract sebanyak 30 gram, dan Agar sebanyak 15 gram ke dalam erlenmeyer.
2. Ditambahkan 50 mL akuades. Hingga dihasilkan MEA sebanyak sebanyak 2,4 gram.
3. Dipanaskan di atas hot plate hingga mendidih sambil diaduk dengan stirer magnetik sampai homogen, lalu dibiarkan beberapa saat.
4. Dimasukkan ke dalam 3 tabung reaksi masing-masing sebanyak 4 mL
5. Disumbat Mulut tabung Reaksi menggunakan kapas
6. Dimasukkan dalam autoklaf untuk disterilkan beserta alat-alat yang akan digunakan pada suhu 121oC dan tekanan 15 psi.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Pengamatan
Tabel 1. Hasil pengamatan Sterilisasi dan Pembuatan Medium Mikroba
No. Media Komposisi
1. Nutrient Agar (NA)
Sebelum Setelah:
Akuades 50 mL
Peptone 5g/L
Meat ekstrak 3 g/L
Agar 17 g/L
Sebelum dipanaskan di atas hot plate berwarna kuning keruh
Setelah dipanaskan di atas hot plate berwarna kuning bening
2. Potato Destroxe Agar (PDA)
Sebelum: Setelah:
Akuades 50 mL
Potato 4 g/L
Glucose 20 g/L ,
Agar 15 g/ L
Sebelum dipanaskan di atas hot plate berwarna putih keruh
Setelah dipanaskan di atas hot plate berwarna putih bening
3. Malt Extract Agar (MEA)
Sebelum: Setelah:
Akuades 50 mL
Malt Ekstrak 30 g/L
Pepton 3 g/L
Agar 15 g/ L
Sebelum dipanaskan di atas hot plate berwarna coklat pucat
Setelah dipanaskan di atas hot plate berwarna coklat tua
4.2 Pembahasan
Media adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat-zat hara (nutrient) yang berguna untuk membiakkan mikroba. Dengan menggunakan bermacam-macam media dapat dilakukan isolasi, perbanyakan, pengujian sifat-sifat fisiologis dan perhitungan sejumlah mikroba. Kegunaan media (perbenihan) dalam laboratorium adalah:
1. Untuk pembiakan dengan maksud memperbanyak bakteri yang dicari.
2. Untuk tujuan isolasi bakteri agar didapat biakan murni.
3. Untuk menyimpan bakteri yang telah murni tersebut baik untuk keperluan sehari-hari (determinasi) maupun untuk menyimpan dalam waktu lama.
4. Untuk mempelajari sifat-sifat pertumbuhannya (culture characteristic).
Supaya mikroba dapat tumbuh baik dalam suatu media, maka medium tersebut harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:
a. Harus mengandung semua zat hara yang mudah digunakan oleh mikroba
b. Harus mempunyai tekanan osmosis, tegangan permukaan dan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroba yang akan ditumbuhkan
c. Tidak mengandung zat-zat yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba
d. Harus berada dalam keadaan steril sebelum digunakan, agar mikroba yang di tumbuhkan dapat tumbuh dengan baik.
Dalam percobaan ini, media yang digunakan adal 3 jenis, yaitu Nutrien Agar (NA) yakni dengan komposisi campuran 5 gram pepton, 3 gram meat extract, dan 12 gram Agar; Potato Destroxe Agar (PDA) yakni dengan komposisi campuran 4 gram potato, 20 gram glukosa, dan 15 gram Agar; serta Malt Extract Agar (MEA) yakni dengan komposisi campuran 3 gram pepton, 30 gram meat extract, dan 15 gram Agar. Mikroorganisme yang akan tumbuh pada media pada NA adalah sejenis bakteri, lalu pada PDA adalah sejenis cendawan atau jamuir, kemudian pada MEA adalah yeast atau khamir.
Untuk membuat media agar, masing-masing media yang telah disebutkan dicampurkan dengan 50 ml akuades hingga kemudian diaduk dengan tujuan agar larutan lebih homogen lalu dipanaskan sembil diaduk dengan stirer magnetic. Pemanasan bertujuan agar media tersebut lebih cepat larut dalam akuades karena pada umumnya kenaikan temperatur akan meningkatkan daya larut suatu zat. Setelah media homogen, menuangkan ke dalam tabung reaksi, setelah itu mulut tabung reaksi disumbat dengan kapas untuk menghindari kontaminasi, atau masuknya mikroorganisme dari luar. Kemudian melakukan sterilisasi menggunakan autoklaf.
Pembuatan medium Potato Dextrose Agar (PDA) ini menggunakan agar untuk mengentalkan medium. Sebelum dilakukan sterilisasi, medium berawarna kuning, setelah disterilisasi dalam autoklaf medium berwarna kecoklatan dan akan didapat endapan berwarna putih. Setelah didinginkan beberapa saat, medium dapat ditanami fungi/jamur. Pembuatan medium Nutrien Agar (NA) dan Malt Extract Agar (MEA), diawal pengamatan medium sebelum proses sterilisasi berwarna kuning, setelah sterilisasi warna medium akan menjadi agak coklat. Pada pembuatan medium NA ini ditambahkan pepton supaya mikroba cepat tumbuh, karena mengandung banyak N2. Agar yang digunakan dalam proses ini untuk mengentalkan medium sama halnya dengan yang digunakan pada medium PDA yang juga berperan sebagai media tumbuh yang ideal bagi mikroba.
Autoklaf merupakan alat sterilisasi untuk media agar mikroorganisme dapat tumbuh dan berkembang. Di laboratorium terbagi menjadi dua yaitu yang digunakan untuk sterilisasi alat dan medium yang akan dipakai, serta yang digunakan untuk destruksi atau sterilisasi kotor. Rongga di dalam autoklaf tidak boleh terlalu penuh diisi dengan benda-benda yang akan disterilisasikan agar dapat terjadi aliran uap yang cukup baik.
Sterilisasi tidak hanya dilakukan pada awal percobaan saja, tetapi juga perlu dilakukan setelahnya pada bahan yang sudah selesai dipakai dengan cara destruksi. Destruksi adalah suatu cara untuk merusak/menghancurkan bakteri penelitian yang tidak digunakan lagi. Berfungsi agar bahan tersebut tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan yang dikenai/dikontaminasi olehnya.
Sterilisasi merupakan proses penting yang harus dilalui sebelum melakukan penelitian yang berhubungan dengan mikroorganisme. Sterilisasi dilakukan pada semua alat dan dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan, baik peralatan laboratorium maupun medium pertumbuhan mikroba. Melalui sterilisasi, seluruh mikroba patogen dapat mati, sehingga tidak sempat berkembang biak. Sterilisasi pada percobaan ini merupakan sterilisasi secara fisik yang menggunakan panas dari dalam autoklav, di mana panas yang digunakan berasal dari uap air sehingga disebut strerilisasi basah. Dengan kondensasi akan terbentuk embun yang dapat menyebabkan keadaan lembab yang cukup untuk membunuh kuman, sehingga bahan menjadi steril.
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang diperoleh dari percobaan ini adalah :
1. Sterilisasi adalah proses mematikan mikroorganisme dari alat dan bahan yang digunakan agar terhindar dari kontaminasi dan diperoleh keadaan steril.
2. Media adalah kumpulan zat-zat organik maupun anorganik yang digunakan sebagai tempat tumbuh dan mengembangbiakkan mikroorganisme.
3. Nutrien Agar (NA) digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme sejenis bakteri, Potato Destroxe Agar (PDA) digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme seperti cendawan atau jamur/fungi, dan Malt Extract Agar (MEA) untuk pertumbuhan khamir atau yeast.
4. Media-media yang digunakan sebagai tempat isolasi bakteri terdapat berbagai macam sesuai karakteristik penggunaannya.
5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan untuk percobaan ini adalah sebaiknya seluruh praktikan dapat melaksanakan praktikum (tidak diwakilkan beberapa praktikan saja), sehingga semua praktikan memiliki keterampilan dalam mengembangbiakkan mikroorganisme.
DAFTAR PUSTAKA
Atlas, Ronald M. 2005. Hand Book of Media for Environmental Microbiology.
CRC Press. Boca Raton.
Dwidjoseputro, D. 1994. Dasar-Dasar Mikrobiologi. Djambatan. Jakarta.
Fardiaz, S. 1992. Mikrobiologi Pangan I. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Fathir, Fuad. 2009. Media Pertumbuhan Mikroba.
http://fuadfathir.multiply.com/journal/item/2
Diakses pada tanggal 31 Oktober 2010.
Gupte, S. 1990. Mikrobiologi Dasar. Binarupa Aksara. Jakarta.
Pustekkom. 2005. Kegiatan Belajar 1.
http://www.e-dukasi.net/mol/mo_full.php?moid=86&fname=kb1_7.htm
Diakses pada tanggal 31 Oktober 2010.
Suriawiria, U. 2005. Mikrobiologi Dasar. Papas Sinar Sinanti. Jakarta.
Sutedjo. 1991. Mikrobiologi Tanah. Rineka Cipta. Jakarta.
Volk , W. A & Wheeler. M. F. 1993. Mikrobiologi Dasar Jilid 1 Edisi ke 5.
Erlangga. Jakarta.
semoga manfaat
salam senyum sapa pembaca
Bissmillah..
Assalammualaikum
Apa kabar readers?
Semoga dalam keadaan sehat dan ada dalam lindungiNya..
Ini kali kedua saya memposting tulisan tanpa ada unsur langsung "copy+paste" dari file documents di levie..
Karena posting saya sebelumnya ini, murni adalah tugas-tugas dan beberapa outexam saya selama berada dalam area teknik kimia tercinta..
Well...
Postingan pertama itu pada tgl 1 oktober 2010. Tapi akhirny saya simpan di draft, takut dia yg namanya tidak boleh disebut ternyata membaca..
Biar menjadi rahasia saya, kecuali bila dia ternyata menjadi special someone nantinya, baru saya edit dan posting, hehe
siapa tho? Bikin penasaran saja..
Baiklah..
Sebenarny apa tujuan saya menulis lewat mobile ini?
Nah, saya mau curhat pribadi. Jadi..
Saya pernah mengalami suatu teguran secara maya hingga membuat saya menangis sejadinya. Ingin pergi ke pelukan mama, menatapnya hingga perasaan di hati ini luluh. Well, saya tidak bisa menceritakan apa yang saya alami.
Tapi saya ingin menyampaikan, pada kalian yang masih memiliki orang tua lengkap..
Tolong jangan sakiti mereka, tolong utk selalu berbakti pada mereka, lakukan hal yang terbaik.. Sebelum semuanya terlambat, sebelum menyesal, sebelum ada teguran nyata yang datang..
Wallohualam Bishowab..
PERCOBAAN 1 BEKERJA DI RUANG PRAKTIK MIKROBIOLOGI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Tujuan Percobaan
Tujuan pada percobaan ini adalah untuk memperkenalkan mahasiswa prinsip-prinsip berpraktikum, alat atau bahan, serta cara penggunaan dan pemeliharaan yang baik.
1.2 Latar Belakang
Berkenaan dengan pentingnya pengamatan dalam penelitian menyebabkan perlunya wadah khusus berupa laboratorium. Dalam penelitian atau praktikum akan diperoleh hasil kualitatif dan hasil kuantitatif dengan berbagai macam cara pengukuran yang menggunakan bermacam-macam peralatan penunjang penelitian/praktikum, sehingga diperlukan pengetahuan khusus tentang fungsi dan berbagai cara penggunaan alat-alat tersebut (Brady, 1999).
Praktikum di laboratorium merupakan sarana yang efektif untuk melatih dan mengembangkan aspek kognitif dan psikomotorik praktikan serta jiwa kerjasama antar praktikan satu dan lainnya. Pengamatan dan percobaan menghasilkan data kualitatif yang didapat melelui pengukuran. Dalam mengukur harus memerhatikan keabsahan yang menyangkut alat ukur, dan juga kuantitas pengukuran yang menyangkut dari segi kecermatan dan ketelitian
(Tim Dosen Teknik Kimia, 2009).
Yang melatarbelakangi percobaan ini adalah bahwa apabila bekerja di laboratorium sebaiknya lebih dulu kita untuk mengenal beberapa alat-alat laboratorium. Salah satunya yang telah dikerjakan ini yaitu dalam skala laboratorium mikrobiologi, yakni mengamati beberapa mikroba yang berskala mikro dan tak kasat mata. Jadi agar diupayakan antara alat dan bahan harus pada keadaan steril, serta kita dapat mengetahui tata cara melakukan kerja praktikum dengan prosedur yang ada sebagai permulaan.
BAB II DASAR TEORI
Salah satu hal yang menunjang dalam pembelajaran mikrobiologi adalah laboratorium. Laboratorium digunakan untuk melakukan percobaan-percobaan yang dilakukan untuk memahami lebih dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan jasad renik. Bekerja di ruang laboratorium mikrobiologi sebelumnya harus mengetahui prinsip-prinsip penggunaan dan pemeliharaan alat serta fungsi. Dengan demikian dalam pelaksanaannya dapat terhindar dari kerusakan alat, kesalahan-kesalahan dalam prosedur kerja, dan diperoleh hasil yang baik, tidak terkontaminasi oleh bahan lain (Frobisher, 1974).
Ada teknik-teknik dasar tertentu yang harus dipelajari oleh para peneliti mirobiologi untuk digunakan dalam laboratorium. Teknik ini digunakan untuk memelihara bakteri, mengisolasinya dalam biakan murni (hanya mengandung satu bakteri), mengamatinya, dan mengidentifikasi mikroorganisme. Dalam praktiknya, kajian mikrobiologi dapat dihadapkan dengan yang namanya mikroorganisme, jasad renik, dan mikroba hingga pengamatan yang dilakukan di bawah mikroskop (Volk, 1993).
Dalam praktikum, analis yang baik biasanya cermat dalam hal kerapian. Mahasiswa dengan meja praktikum yang tertib, kecil kemungkinan mencampuradukkan sampel, salah menambah reagensia, menumpahkan larutan, dan memecahkan alat kaca. Kerapian dalam laboratorium tentu saja harus melebar mulai dari meja praktikumnya sendiri ke beberapa rak dimana tersedia bahan-bahan untuk seluruh kelas. Banyak waktu terbuang untuk mencari sebuah benda kecil dalam kumpulan alat kaca yang berantakan atau untuk mencuci suatu botol reagensia tertentu yang salah ditaruh pada rak samping. Kerapian hendaknya mencakup juga pemeliharaan perabot laboratorium yang permanen seperti oven, lemari asam, bak meja. Bahkan korosif yang tumpah harus segera dikeringkan dari peralatan, bangku, ataupun lantai. Penting bahwa saluran pembuangan disterilkan dengan mengguyur asam dan basa dengan banyak air. Analisis tidak boleh dilakukan dengan alat kaca yang tidak bersih. Alat kaca yang tampaknya bersih, belum tentu bersih dari sudut pandang seorang analis. Permukaan yang tampaknya tak ada kotoran, sering masih tercemari oleh lapisan tipis tak tampak yang berminyak (Day, 1999).
Prinsip-prinsip pemeliharaan mikroskop dan penggunaannya harus diketahui oleh praktikan karena beberapa bagian mikroskop rentan terhadap partikel asing, mengalami disfungsi, harganya relatif mahal dan mudah pecah, sehingga mikroskop harus disimpan dalam kotak khusus, bila dipindahkan caranya harus dengan kuat dan hati-hati dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri menopang pada bagian bawah statif (Dwidjoseputro, 1994).
Peralatan yang digunakan di laboratorium mikrobiologi selain mikroskop adalah tabung reaksi, beaker glass, labu ukur, gelas ukur, cawan petri, pipet volumetrik, buret, jarum inokulasi atau jarum ose, oven (hot air sterilizer), autoclave, lampu spritus dan pembakar gas “bunsen”, alat timbangan (neraca analitik), pH meter, inkubator, freezer, hemocytometer, spectonic 20 D, colony counter, hot plate, vortex mixer, dan lain sebagainya. Peralatan yang tersebut di atas merupakan sebagian kecil dari peralatan yang terdapat di laboratorium mikrobiologi yang fungsi dan cara penggunaannya harus diketahui oleh praktikan (Sutedjo, 1991).
Autoklaf digunakan sebagai alat sterilisasi uap dengan tekanan tinggi. Penggunaan autoklaf untuk sterilisasi, tutupnya jangan diletakkan sembarangan dan dibuka-buka karena isi botol atau tempat medium akan meluap dan hanya boleh dibuka ketika manometer menunjukkan angka 0 serta dilakukan pendinginan sedikit demi sedikit. Medium yang mengandung vitamin, gelatin atau gula, maka setelah sterilisasi medium harus segera didinginkan. Cara ini untuk menghindari zat tersebut terurai. Medium dapat langsung disimpan di lemasi es jika medium sudah dapat dipastikan steril (Dwidjoseputro, 1994).
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan alat-alat praktikum:
1. Mengeringkan alat-alat
Gelas setelah dicuci diletakkan terbalik. Hanya bagian luar yang dilap. Bagian dalam dan bagian lain yang berhubungan dengan pereaksi-pereaksi tidak boleh dilap. Bila bagian dalam perlu lekas kering, alat dipanaskan sedikit.
2. Tutup botol
Pada tutup yang bagian atasnya datar, letakkan terbalik. Bila tutup botol berbentuk paruh, tutup jangan dicabut, membuka dan menutup botol ini dengan cara mengatur saluran pada botol dan tutup.
3. Menuangkan cairan dari botol beretiket
Etiket harus dipegang menghadap telapak tangan dan cairan dialirkan dari sisi yang berjauhan dengan etiket, supaya cairan yang mengalir pada dinding luar botol tidak merusak etiket, jadi isi botol dapat selalu diketahui dengan mudah.
.4. Mencium isi botol
Jangan mencium secara langsung, tapi dengan mendekatkan hidung ke mulut botol lalu melambaikan tangan di atas mulut botol menuju hidung.
5. Menimbang
Yang harus diperhatikan dalam menimbang adalah:
1. Penimbangan harus dilakukan dalam ruangan tertutup.
2. Meletakkan dan mengambil anak timbangan dengan pinset.
3. Dilarang menimbang barang panas sebelum didinginkan.
4. Jaga selalu kebersihan timbangan.
Alat-alat gelas volumetrik harus bersih dan bebas dari lemak. Alat-alat volumetrik tersebut terlebih dahulu dibersihkan dengan detergen. Apabila masih sulit dihilangkan, maka dapat digunakan larutan bikromat (K2Cr2O7 atau H2Cr2O7) dan kemudian alat-alat tersebut disimpan dengan posisi terbalik
(Tim Dosen Teknik Kimia, 2009).
Bahan atau peralatan yang digunakan dalam bidang mikrobiologi harus dalam keadaan steril. Steril artinya tidak didapatkan mikroba yang tidak diharapkan kehadirannya baik yang mengganggu atau yang merusak media atau mengganggu kehidupan dan proses yang sedang dikerjakan. Setiap proses baik fisika, kimia, maupun mekanik yang membunuh semua bentuk kehidupan terutama mikroorganisme disebut dengan sterilisasi (Waluyo, 2005).
BAB III METODOLOGI PERCOBAAN
3.1 Alat
Alat-alat yang diamati dalam praktikum ini antara lain adalah Waterbath, Oven, Shaker, Mikroskop Listrik, Colony Counter, Inkubator, Autoklaf, Jarum ose, Sentrifuge, Bunsen, Pengaduk, Hot Plate Stirrer, Laminary Air Flow Cabinet (LAF), Vortex mixer, Lemari bahan dan lemari alat, Stirrer magnetic, Tabung reaksi, Cawan petri, Gelas ukur, Pipet Mikro dan Tip pipet, Refrigerator Incubator, Freezer, dan Spektronik 20 D+.
3.2 Bahan
Bahan-bahan yang diamati pada praktikum ini adalah akuades dan kapas.
3.3 Prosedur Kerja
1. Diamati berbagai alat-alat yang terdapat dalam laboratorium Mikrobiologi.
2. Didokumentasikan alat-alat tersebut.
3. Dipahami berbagai fungsi masing-masing alat serta cara perawatannya.
4. Diketahui kelebihan dan kekurangan dari alat-alat tersebut.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Pengamatan
Tabel 4.1 Hasil Pengamatan Peralatan Laboratorium Mikrobiologi
No Nama Alat Gambar Fungsi dan Keterangan
1. Waterbath
Untuk mengkonstankan suhu cairan disekitarnya dan memanaskan cairan.
2. Oven
Merupakan alat sterilisasi udara kering dan juga untuk sterilisasi alat.
3. Shaker
Untuk menghomogenkan lartan atau cairan dalam jumlah skala besar.
4. Mikroskop Listrik
Untuk melihat objek yang sangat kecil (berukuran mikroskopik) seperti mikroba yang akan diteliti.
5. Colony Counter
Untuk menghitung jumlah biakan mikroba yang ada di dalam cawan petri per satuan koloni.
6. Inkubator
Untuk menginkubasi dan tempat menumbuhkan mikoba.
7. Autoklaf
Untuk sterilisasi alat-alat dengan menggunakan prinsip uap bertekanan tinggi dengan tekanan 1-2 Atm, suhu 121 0C (sterilisasi udara basah).
8. Jarum ose Untuk menginokulasikan biakan mikroba dalam tahap mengisolasi mikroba.
9. Sentrifuge
Untuk memisahkan bagian senyawa-senyawa molekul, partikel sederhana yang sederhana yang bercampur dalam suatu larutan koloid.
10. Bunsen
Untuk sterilisasi alat dengan menggunakan proses pembakaran (insinerasi). Biasanya alat yang di sterilisasi spiritus adalah jarum ose.
11. Pengaduk
Untuk mengaduk dan mencampur suatu bahan secara manual.
12. Hot Plate Stirrer
Untuk memanaskan atau menghomogenkan suatu cairan (media).
13. Laminary Air Flow Cabinet (LAF)
Untuk mengisolasi mikroba atau tempat untuk ruangan steril.
14. Vortex mixer
Untuk menghomogenkan suatu campuran zat dalam jumlah skala kecil.
15. Lemari bahan dan lemari alat
Untuk menyimpan semua bahan dan peralatan laboratorium.
16. Stirer magnetic
Berfungsi mengaduk cairan agar homogen
17. Tabung reaksi
Berfungsi mereaksikan zat dan sebagai wadah pembiakan mikroba dengan media cair.
18. Cawan petri
Tempat untuk untuk menanam/. menumbuhbiakkan mikroba.
19. Gelas ukur
Sebagai alat mengukur volume mengukur volume jumlah cairan dengan volume tertentu.
20. Pipet Mikro dan Tip pipet
Untuk mengambil larutan dalam skala volume tertentu.
21. Refrigerator Incubator
Untuk menyimpan isolat mikroba dan lain-lain pada suhu tertentu.
22. Freezer
Untuk menyimpan biakan mikroba dengan suhu mencapai titik beku air.
23. Spektronik 20 D+
Alat yang digunakan dalam perhitungan mikrobia berdasarkan kekeruhan atau turbidimetri.
1.2 Pembahasan
Untuk menjalankan fungsinya. laboratorium harus di lengkapi dengan peralatan yang cukup memadai dan selalu dalam keadaan siap pakai. Alat-alat gelas merupakan salah satu peralatan yang harus dimiliki oleh suatu laboratorium, contohnya laboratorium Mikrobiologi. Sifat gelas yang tidak dapat bereaksi dengan zat-zat kimia menyebabkan alat gelas sangat diperlukan dalam suatu laboratorium dan juga karena pada beberapa praktik dan percobaan di Laboratorium Mikrobiologi memerlukan bahan-bahan atau larutan yang tahan panas tinggi, juga peralatan gelas bersifat cepat panas dan mudah dibersihkan dari kotoran bekas larutan.
Adapun alat-alat gelas yang umum terdapat dalam suatu laboratorium antara lain seperti wadah-wadah gelas, alat gelas untuk mereaksikan zat ialah tabung reaksi, kemudian untuk mengukur volume meliputi gelas ukur dan pipet mikro, dan alat gelas lainnya seperti pengaduk gelas, gelas arloji, dll. Perlu adanya pemeliharaan secara khusus terhadap alat-alat gelas sangat diperlukan, yaitu dengan cara membaca petunjuk penggunakan jika disediakan, membaca petunjuk praktikum dengan cermat, jangan menggunakan alat gelas yang belum diketahui fungsinya, berhati-hati dalam bekerja, membersihkan kembali alat-alat gelas dan menyimpan kembali alat-alat gelas pada tempatnya setelah digunakan.
Tabung reaksi, terbuat dari gelas dan dapat dipanaskan, terutama digunakan untuk mereaksikan zat-zat kimia dalam jumlah sedikit, jika dilakukan pengocokan kesamping tabung tidak boleh diisi lebih dari setengahnya. Jika dilakukan pemanasan, harus dilakukan dengan hati-hati, tabung dipegang miring. Gelas ukur, digunakan untuk mengukur volume zat kimia dalam bentuk cair. Gelas ini bersekala dan terdiri atas bermacam-macam ukuran. Tidak boleh digunakan untuk mengukur larutan atau pelarut panas. Dan pipet mikro, untuk mengambil larutan/cairan dalam skala volume tertentu, yakni dengan cara mengeluarkan/meneteskan larutan dengan tepat dalam skala mikro.
Alat-alat gelas dapat dibersihkan dengan menggunakan sabun dan air keran. Gunakan sikat yang sesuai dalam hal ukuran dan kehalusan. Bilas peralatan gelas mula-mula dengan air keran, kemudian satu atau dua kali dengan akuades. Kadang-kadang beberapa alat ukur volume perlu direndam beberapa lama dalam air sabun dan K2Cr2O7 dan H2SO4 bila kotoran sulit dihilangkan. Dibalikkan peralatan yang telah bersih diatas serbet/kain. Jangan mengeringkan peralatan gelas yang ditera dengan teliti di dalam oven atau diatas api langsung tanpa ada perantara. Bilaslah peralatan gelas dengan pelarut atau larutan yang akan digunakan.
Alat gelas adalah benda yang transparan, lumayan kuat, biasanya tidak bereaksi dengan bahan-bahan kimia, dan tidak aktif secara biologi yang bisa dibentuk dengan permukaan yang sangat halus dan kedap air. Oleh karena sifatnya yang sangat ideal gelas banyak digunakan di banyak bidang kehidupan. Tetapi gelas bisa pecah menjadi pecahan yang tajam. Sifat kaca ini bisa dimodifikasi dan bahkan bisa diubah seluruhnya dengan proses kimia atau dengan pemanasan.
Adapun alat-alat selain alat gelas yang telah disebutkan di atas digunakan di dalam suatu laboratorium mikrobiologi, yaitu Waterbath, merupakan peralatan yang berfungsi untuk menstabilkan suhu cairan disekitarnya. Dengan alat ini suhu dapat dijaga agar tetap (konstan). Kelemahan alat ini yaitu tidak dapat dimuat dengan alat-alat dalam jumlah besar atau ukuran yang besar dan alat ini merupakan alat elektronik yang bergantung pada suplai listrik. Oven, berfungsi untuk sterilisasi alat-alat yang akan digunakan (terutama alat-alat gelas) dengan cara memanaskan peralatan tersebut pada suhu diatas 80°C karena mikroorganisme pada umumnya mati pada suhu sekitar itu. Penggunaan oven dalam sterilrilisasi alat biasanya disebut sterilisasi udara kering. Kelebihan oven yaitu lebih praktis dalam hal sterilisasi alat karena cukup dengan memasukkan alat-alat saja dan mengatur suhunya saja. Sedangkan kelemahannya yaitu membutuhkan waktu sterilsasi yang lebih lama dan tidak dapat digunakan untuk sterilisasi peralatan plastik.
Shaker, alat ini mempunyai fungsi untuk menghomogenkan campuran bahan yang digunakan untuk membuat media. Kelebihan shaker yaitu dapat menghomogenkan campuran secara otomatis, alat yang digunakan bersama shaker biasanya erlenmeyer, shaker tidak dapat mengocok media pada wadah yang terlalu kecil seperti tabung reaksi. Mikroskop Cahaya Listrik, berfungsi untuk mengamati objek berupa mikroba yang akan diteliti. Kelebihannya yaitu mikroskop ini tidak bergantung pada pencahayaan dari lingkungan seperti mikroskop cahaya biasa pada umumnya karena kebutuhan cahaya dipenuhi oleh lampu listrik dibawah kaca objek. Kekurangannya yaitu perbesarannya hanya terbatas pada 1000x perbesaran saja.
Colony Counter, yaitu alat yang memiliki lensa pambesar berfungsi untuk menghitung populasi mikroba pada cawan petri. Alat ini juga dilengkapi dengan kounter manual yang digunakan sebagai penentu banyaknya bakteri yang sudah dihitung. Kelebihan lainnya yaitu penghitungan bakteri secara langsung sambil mengamati morfologi bakteri/mikroba yang telah tumbuh. Kekurangannya yaitu penghitungan dilakukan dalam waktu yang relatif lama karena perhitungan dilakukan secara manual. Inkubator, yaitu alat yang memiliki kinerja mirip dengan oven ini berfungsi untuk menginkubasi atau menumbuhkan mikroba dengan beberapa penyesuaian kondisi sehingga mikroba dapat tumbuh dengan baik bahkan dapat pula dibuat kondisi khusus agar hanya satu jenis mikroba (biakan murni) yang dapat tumbuh, suhu pada inkubator dapat diubah-ubah sesuai dengan keperluan. Kelemahan inkubator sebagai alat laboratorium yaitu tidak dapat menampung pembiakan mikroba secara besar-besaran, karena inkubator ini bukan dalam skala produksi tapi hanya pada skala sampel.
Autoklaf mempunyai fungsi yang sama dengan oven yaitu untuk mensterilisasi peralatan yang akan digunakan, hanya saja pada prosesnya melibatkan uap air bertekanan tinggi. Cara sterilisasinya sering disebut sterilisasi udara basah. Pada saat disterilisasi keadaan didalam autoklaf dikondisikan pada suhu 121°C dan tekanan 1-2 atm (15 psi), kelemahan alat ini yaitu relatif lebih rumit penggunaannya serta lebih berbahaya dan juga ketergantungan alat ini pada sumber listrik sehingga apabila aliran listrik terhenti maka alat ini tidak dapat digunakan. Kelebihan alat ini yaitu lebih efektif dalam sterilisasi karena uap-uap panas dan jenuh dapat menembus dan mencapai banyak luas permukaan sehingga dalam waktu yang relatif singkat. Jarum ose, yaitu alat yang terbuat dari logam dan ujungnya berbentuk bulat atau lancip dan terbuat dari kawat ini berfungsi untuk menggores media yang akan ditumbuhi mikroba. Dengan jarum ose dapat diambil sejumlah mikroba dan menggoreskanya pada media, dengan begitu mikroba akan tumbuh berdasarkan pla goresan yang dibentuk. Goresan yang dibentuk saling menyambung meskipun jarum ose selalu dipijarkan ketika hendak embuat goresan baru, hal tersebut dimaksudkan agar didapatkan mikroba tunggal (individu). Kelemahannya yaitu karena alat yang sederhana dan manual maka hasil yang akan diperoleh sangat bergantung dari keterampilan pemakainya.
Sentrifuge, berfungsi untuk memisahkan komponen yang lebih padat dengan komponen cair yang bercampur dalam sebuah larutan koloid. Kelamahan dari sentrifuge yaitu tidak dapat memisahkan dua zat yang bercampur secara sempurna (larutan sejati). Bunsen, merupakan peralatan sterilisasi yang pada proses sterilisasinya hanya dengan memijarkan alat yang akan disterilisasi. Biasanya peralatan yang disterilisasi dengan lampu spiritus adalah jarum ose, tentunya peralatan yang akan disterilisasikan dengan alkohol 70%. Keunggulan spiritus yaitu dapat mensterilisasi peralatan dengan cepat dan praktis selain itu spiritus juga dapat mensterilkan udara yang berada dijangkauan radiasi panas efektif untuk membunuh mikroba oleh karena itu pada proses inokulasi mulut tabung reaksi didekatkan pada nyala api spiritus. Kekurangannya yaitu tidak dapat mensterilisasi peralatan dalam skala besar.
Hot Plate dan Magnetic Stirer, berfungsi untuk memanaskan bahan atau media (mencairkan media). Bisa juga digunakan untuk membantu pencampuran dua bahan yang pada proses pencampurannya memerlukan pemanasan. Kelemahan hot plate yaitu tidak dapat diatur secara tepat suhunya dan juga tidak dapat dikondisikan untuk mempertahankan suhu karena akumulasi panas akan menyebabkan kenaikan suhu secara perlahan. Biasanya dalam pencampuran menggunakan hot plate juga digunakan magnetic stirer yang berfungsi untuk mengaduk-aduk bahan yang dicampurkan. Jadi, kita tidak perlu mengaduk secara manual.
Laminary Air Flow Cabinet (LAF), yaitu alat yang berbentuk seperti lemari kaca dan berfungsi untuk wadah khusus atau ruang mini untuk proses isolasi suatu mikroba. Laminary flow dilengkapi juga dengan blower (semacam pengering yang menghembuskan udara), sinar UV (yang berfungsi untuk mensterilkan lingkungan di dalam laminary flow) dan lampu untuk penerangan. Kekurangan alat ini yaitu tidak dapat digunakan sebagai wadah untuk mengisolasi mikroba dala skala besar. Vortex mixer, alat ini mempunyai fungsi untuk menghomogenkan campuran bahan, hanya saja alat-alat yang dapat dikocok dengan vortex mixer ini lebih kecil seperti tabung reaksi. Kelemahannya yaitu tidak dapat mengocok dengan efektif untuk peralatan yang lebih besar atau peralatan selain tabung reaksi karena arah kocokan berputar.
Lemari bahan dan lemari alat, berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan maupun alat-alat yang akan digunakan. Lemari ini juga berfungsi untuk meminimalisasi gangguan luar sehingga alat-alat maupun bahan tidak rusak. Kelemahannya yaitu karena lemari ini terbuat dari kayu maka masih ada kemungkinan kontaminan masuk dan mengotori alat maupun bahan. Cawan petri, alat ini berfungsi sebagai wadah media yang akan ditumbuhi mikroba (wadah menanam mikroba), alat gelas ini mempunyai kelebihan berupa kemudahan dalam proses perhitungan mikroba karena pembiakan mikroba dilakukan dalam sekala kecil sehingga dapat diambil sampel dengan perbandingan tertentu. Kelemahannya yaitu tidak dapat digunakan dalam pembiakan mikroba skala besar. Spektronik 20 D+, yakni alat elektronika ini berfungsi untuk menghitung populasi mikroba berdasarkan tingkat kekeruhannya atau konsentrasi mikroba di dalam media cair yang bening. Alat ini dapat menghitung mikroba secara matematis hanya dari tingkat kekeruhannya hanya jika media tidak keruh dan proses perhitungannya singkat. Kelemahan alat ini yaitu tidak menghitung jumlah mikroba yang sebenarnya.
Pada umumnya, alat-alat gelas merupakan peralatan yang mudah pecah, sehingga sebelum dipergunakan alat-alat gelas harus diperiksa apakah ada cacat serta kebersihannya dengan teliti. Apabila ternyata alat tersebut retak maka jangan diteruskan untuk menggunakannya. Kebersihan alat juga sangat penting dalam suatu laboratorium karena dapat mempengaruhi hasil percobaan, apalagi dalam skala laboratorium mikrobiologi ini kita dituntut untuk selalu dalam keadaan bersih dan steril. Data yang dihasilkan dapat menjadi tidak akurat jika percobaan dilakukan dalam wadah yang terkontaminasi.
Sedangkan untuk yang bukan merupakan alat gelas, maka hendaknya digunakan sesuai dengan ketentuan dan cara pemakaiannya supaya alat tersebut dapat berfungsi dalam jangka waktu yang lama. Mengetahui peralatan praktikum dalam suatu laboratorium merupakan hal yang wajib bagi praktikan. Hal ini sangat penting karena banyak peralatan praktikum yang dapat membahayakan jika terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Oleh karena itu, ketelitian dalam penggunaan dan cara pemeliharaan sangat diperlukan.
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang diperoleh dari percobaan ini adalah :
1. Laboratorium harus di lengkapi dengan peralatan yang cukup memadai dan selalu dalam keadaan siap pakai. Sifat gelas yang tidak dapat bereaksi dengan zat-zat kimia menyebabkan alat gelas sangat diperlukan dalam suatu laboratorium dan juga karena pada beberapa praktik dan percobaan di laboratorium.
2. Alat-alat gelas merupakan peralatan yang mudah pecah sehinga sebelum dipergunakan alat-alat gelas harus diperiksa apakah ada cacat serta kebersihannya dengan teliti.
3. Contoh peralatan yang ada di laboratorium mikrobiologi adalah inkubator, colony counter, sentrifuge, jarum ose, autoclave, destilator, water bath, mikroskop, cawan petri, dan lain-lain.
4. Pemeliharaan secara khusus terhadap alat-alat gelas sangat diperlukan yaitu dengan cara membaca petunjuk penggunakan jika disediakan, membaca petunjuk praktikum dengan cermat, jangan mnggunakan alat gelas yang belum diketahui fungsinya, hati-hati dalam bekerja, membersihkan kembali alat-alat gelas dan menyimpan kembali alat-alat gelas pada tempatnya setelah digunakan.
5.2 Saran
Saran yang dapat disampaikan pada percobaan ini adalah hendaknya dalam praktikum assisten maupun praktikan mampu mengatur waktu pengamatan agar praktikum dapat berjalan efisien.
DAFTAR PUSTAKA
Brady, J. E. 1999. Kimia Universitas. Binarapa Aksara. Jakarta.
Day, R.A.Jr and A.L. Underwood,1999, Analisis Kimia Kuantitatif Edisi Keenam. Penerbit Erlangga. Jakarta.
Dwidjoseputro. 1994. Dasar-Dasar Mikrobiologi. Djambatan. Jakarta.
Frobisher, dkk. 1974. Fundamentals of Microbiology. Saunders Company. London.
Lim, D. 1998. Microbiology 2nd Edition. McGraw-Hill book. New York.
Sutedjo. 1991. Mikrobiologi Tanah. Rineka Cipta. Jakarta.
Tim Dosen Teknik Kimia. 2009. Penuntun Praktikum Kimia Dasar. Universitas Lambung Mangkurat. Banjarbaru
Volk, W. A. dan Wheeler, M. F. 1993. Mikrobiologi Dasar Edisi Kelima. Erlangga. Jakarta.
Waluyo, Lud. 2005. Mikrobiologi Umum. UMM Press. Malang.
semoga manfaat
Makalah natrium karbonat
BAB IPENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Yang melatarbelakangi makalah ini adalah untuk pengetahuan senyawa yang bernama natrium karbonat. Dalam keseharian kita biasa menyebutnya soda kue dan produksinya sangat banyak. Namun kita belum pernah tahu bagaimana cara pembuatan senyawa ini dan analisa kation anionnya sangat diperlukan untuk identifikasinya. Karena bila natrium bikarbonat diuraikan dari senyawanya, maka akan terbentuk ion, yakni positif yang disebut kation dan negatif yang disebut anion. Dan ionnya ini bila berdiri sendiri maka akan mempunyai fungsi yang berlainan lagi.
1.2 TUJUAN
Untuk mengenal senyawa natrium bikarbonat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya mengenalnya hanya dengan sebutan soda kue, tapi juga senyawa yang bersifat fungsional. Karena setiap senyawa memiliki lebih dari satu fungsi, namun terkadang juga memiliki beberapa kelemahan.
BAB II PEMBAHASAN
2.1 SENYAWA NaHCO3
Senyawa ini memiliki nama IUPAC adalah Sodium bicarbonate atau sodium hydrogen carbonate, natrium bikarbonat atau natrium hidrogen karbonat. Dengan nama trivial backing soda atau soda kue. NaHCO3 berbentuk Kristal padatan/solid yang berwarna putih. Senyawa ini memiliki bilangan atom 72. Merupakan ikatan ionik. Larut dalam senyawa polar, air.
Natrium karbonat adalah senyawa yang bersifat amfoter. Pemecahan larutannya adalah dengan cara pendinginan dari sifat alkali pada natrium untuk pembentukan asam karbonat dan ion hidroksida.
HCO3- + H2O → H2CO3 + OH−
Inilah gambar dari senyawa NaHCO3:
1.1G Pada soda kue
1.2G Pada minuman
2.2 IDENTIFIKASI SENYAWA
Analisa ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk kation dan anion. Perhatikan reaksi peruraian berikut ini:
NaHCO3(s) → Na+ + HCO3-
2.2.1 Kation pada natrium
Natrium sebagai memiliki bilangan atom 11 yang merupakan logam reaktif yang lunak, keperakan, dan seperti lilin, dan termasuk dalam golongan logam alkali yang banyak terdapat dalam senyawa alam. Dalam uji nyala api berwarna kuning dan beroksidasi dalam udara dan bereaksi kuat dengan air sehingga harus disimpan dalam minyak. Karena sangat reaktif natrium hampir tidak pernah ditemukan sebagai unsur murni di alam.
Natrium mengapung di air, menguraikannya gas hidrogen dan ion hidroksida. Jika digerus menjadi bubuk, natrium akan meledak dalam air secara spontan.namun biasanya tidak meledak dalam udara bersuhu 388 Kelvin. Namun bila dalam bentuk ion positif Na+ maka bilangan atomnya menjadi 10.
Klasifikasi kation yang paling umum didasarkan pada perbedaan kelarutan dari klorida, sulfida, dan karbonat kation tersebut. Kation diklasifikasikan dalam 5 golongan berdasarkan sifat-sifat kation tersebut terhadap beberapa reagensia.
Dari kelima klasifikasi tersebut, Kation Na+ masuk identifikasi golongan V, yaitu golongan sisa karena tidak bereaksi dengan reagensia-reagensia golongan sebelumnya. Ion kation yang termasuk dalam golongan ini antara lain magnesium, natrium, kalium. Ammonium, litium, dan hidrogen. Jadi, penulisan reaksinya adalah langsung pada kationnya.
Na+ + e- → Na
2.2.2 Anion pada HCO3-
Adapun HCO3- memiliki bilangan atom 62. HCO3- adalah ion negatif yang merupakan system penyangga utama cairan luar sel(darah) yang nantinya berpasangan dengan H2CO3.
Sistem penyangga keduanya menjaga pH darah hamper konstan yaitu sekitar 7,4. Perbandingan ion bikarbonat dengan asam karbonat yang diperlukan harus 20 : 1. Jumlah ion karbonat yang relatif jauh lebih banyak diperlukan itu dapat dimengerti karena hasil-hasil metabolisme yang diterima darah lebih banyak yang bersifat asam. Proses metabolisme dalam jaringan, terus-menerus membebaskan asam-asam seperti asam laktat, asam pospat, dan asam sulfat.
Ketika asam-asam itu memasuki pembuluh darah, maka ion bikarbonat akan berubah menjadi asam karbonat, kemudian terurai membentuk karbon dioksida. Pernapasan akan meningkat untuk mengeluarkan kelebihan CO2 dalam paru-paru. Apabila darah menerima zat basa, maka asam karbonat berubah menjadi ion bikarbonat. Untuk mempertahankan perbandingan 20 : 1 tadi, maka sebagian CO2 yang terdapat dalam paru-paru akan larut dalam darah membentuk asam karbonat.
Analisa anion dari CO32- terdapat pada golongan D adalah dengan reaksi berikut:
1. CO32- + AgNO3 → Ag2CO3 putih + 2NO3-
Ag2CO3 + 2NO3- → 2AgNO3 + H2CO3
2. CO32- + Mg(SO4)2 → MgCO3 putih + 2SO42
Metode untuk mendeteksi anion memang tidak sesistematik seperti yang digunakan untuk kation. Namun skema klasifikasi pada anion bukanlah skema yang kaku karena beberapa anion termaksud dalam lebih dari satu golongan.
3.3 KEGUNAAN SENYAWA NaHCO3
NaHCO3 dalam penyebutannya kerap disingkat menjadi bicnat. Senyawa ini termasuk kelompok garam. Senyawa ini kebanyakan digunakan dalam roti atau kue karena bereaksi dengan bahan lain membentuk gas karbon dioksida, yang menyebabkan roti "mengembang". Senyawa untuk membuat kue menjadi mengambang ini disebut backing powder yakni campuran serbuk natrium bikarbonat dengan suatu zat yang bersifat asam, seperti kalium hydrogen tartrat (KHC4H4O6). Campuran bubuk itu tidak beraksi dalam kering karena bicnat hanya larut dalam air. Namun sekali bubuk itu berada dalam adonan, keduanya akan bereaksi menghasilkan gas karbon dioksida yang memekarkan adonan.
Senyawa ini juga digunakan sebagai obat antasid (penyakit maag atau tukak lambung). Karena bersifat alkaloid (basa), senyawa ini juga bisa digunakan sebagai obat penetral asam bagi penderita asidosis tubulus renalis (ATR) atau rhenal tubular acidosis (RTA). Bisa juga digunakan untuk membersihkan barang-barang yang terbuat dari plastik.
Selain itu bisa juga untuk membersihkan perak, caranya masukkan perak dalam air yang baru direbus. Tambahkan satu sendok baking soda, garam dapur (NaCl) dan sepotong kertas aluminium. Lalu diamkan selama kira-kira 15 menit. Selanjutnya keringkan dengan kain lembut yang kering.
Natrium bikarbonat umumnya diproduksi melalui proses Solvay kira-kira 100000 ton/tahun, yang memerlukan reaksi natrium klorida, amonia, dan karbon dioksida dalam air.
Berikut adalah proses solvay:
Di udara karbon dioksida mengikat natrium hidroksida, terbentuk senyawa natrium karbonat(soda abu) dan uap air.
CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O
Lalu dengan natrium karbonat mengikat CO2 dalam air
Na2CO3 + CO2 + H2O → 2 NaHCO3
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN
Dari pembahasan di atas, disimpulkan bahwa:
1) NaHCO3 merupakan senyawa yang tidak asing bagi manusia karena sangat banyak digunakan oleh para pembuat kue.
2) Kegunaan natrium bikarbonat sebagai senyawa berbeda dengan kegunaannya dalam bentuk ion, bila diuraikan menjadi ion natrium positif dan ion bikarbonat negatif.
3) Karena merupakan senyawa ionik, maka larut dalam pelarut polar, contohnya air.
Untuk beberapa senyawa yang memiliki kegunaan tertentu, belum tentu kegunaan itu bersifat menguntungkan. Karena ada beberapa senyawa sod yang digunakan untuk hal-hal yang merugikan. Untuk itu, perlu suatu etiket untuk hal ini, yakni kesadaran tiap-tiap manusia untuk menggunakan bahan dari senyawa yang ada, karena jika salah penggunaan akan berbahaya untuk nantinya.
DAFTAR PUSTAKA
Harjadi, W. 1993.Ilmu kimia analitik Dasar .Erlangga. Jakarta
Purba, Michael. 2004. Kimia SMA 2B. Erlangga. Jakarta
Underwood & R.A Day. 1986. Analisis Kimia Kuantitatif. Erlangga. Jakarta
Vogel. 1990. Analisis Anorganik Kualitatif. PT. Kalman Media Pustaka. Jakarta
http://diytrade.com (diakses tanggal 2 November 2009)
http://tjmlchem.en.alibaba.com (diakses tanggal 2 November 2009)
http://www.banjarmasinpost.co.id (diakses tanggal 2 November 2009)
semoga manfaat
MAKALAH SOAL OPEN ENDED OSN PTI PERTAMINA 2010
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Metanol sebagai alternatif bahan bakar masih untuk saat ini masih kurang mendapat perhatian daripada bahan bakar etanol. Penggunaan metanol terbanyak adalah sebagai bahan pembuat bahan kimia lainnya. Sekitar 40% metanol diubah menjadi formaldehyde, dan dari sana menjadi berbagai macam produk seperti plastik, plywood, cat, peledak, dan tekstil. Dalam beberapa pabrik pengolahan air limbah, sejumlah kecil metanol digunakan ke air limbah sebagai bahan makanan karbon untuk denitrifikasi bakteri, yang mengubah nitrat menjadi nitrogen.
Skala industri produksi methanol bisa dihasilkan dengan menggunakan gas alam (metana) sebagai bahan baku. Saat ini, gas sintesis umumnya dihasilkan dari metana yang merupakan komponen dari gas alam. Metanol pada umumnya bisa diproduksi dengan proses pirolisis dari dari bahan berbasis selulosa misal kayu, jerami, alang-alang yang dikenal sebagai biomas. Pirolisis adalah dekomposisi kimia bahan organik melalui proses pemanasan tanpa atau sedikit oksigen atau reagen lainnya, di mana material mentah akan mengalami pemecahan struktur kimia menjadi fase gas. Sedangkan biomass adalah material yang berasal dari tumbuhan maupun hewan termasuk manusia. Namun biomass dalam sudut pandang industri juga berarti material biologis yang bisa diubah menjadi sumber energi atau material industri.
1.2 Tujuan Penulisan
Tujuan Penulisan Makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui metanol sebagai bahan bakar
2. Pembuatan metanol dengan proses pirolisis dan kegunaannya
3. Keuntungan dan kelemahan metanol.
1.3 Perumusan Masalah
Dengan latar belakang di atas, maka disusunlah perumusan masalah untuk dibahas yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana produksi metanol dari bahan baku biomas?
2. Bagaimana perbandingan kandungan energi metanol yang terdapat pada bahan bakar lainnya?
3. Berapakah konsentrasi metanol yang dapat diblending dengan BBM?
4. Mengapa metanol konsentrasi rendah memiliki banyak kendala dibandingkan dengan BBM yang ada?
5. Jelaskanlah bahan adidtif apa saja yang bisa menghasilkan campuran metanol di atas 20%?
6. Berapa kemungkinan jarak yang bisa ditempuh dalam Km/liter?
7. Sebutkan keuntungan dan kerugian penggunaan metanol sebagai bahan bakar!
1.4 Metode Penulisan
Makalah ini disusun berdasarkan hasil studi literatur yang mengacu pada permasalahan yang telah ditentukan.
BAB II
HASIL DAN PEMBAHASAN
Metanol, juga dikenal sebagai metil alkohol, wood alcohol atau spiritus, adalah senyawa kimia dengan rumus kimia CH3OH. Ia merupakan bentuk alkohol paling sederhana. Kata methyl pada tahun 1840 diambil dari methylene, dan kemudian digunakan untuk mendeskripsikan "metil alkohol". Nama ini kemudian disingkat menjadi "metanol" tahun 1892 oleh International Conference on Chemical Nomenclature. Suffiks [-yl] (indonesia {il}) yang digunakan dalam kimia organik untuk membentuk nama radikal-radikal, diambil dari kata "methyl". Pada "keadaan atmosfer" ia berbentuk cairan yang ringan, mudah menguap, tidak berwarna, mudah terbakar, dan beracun dengan bau yang khas (berbau lebih ringan daripada etanol). Ia digunakan sebagai bahan pendingin anti beku, pelarut, bahan bakar dan sebagai bahan additif bagi etanol industri.
Sedangkan etanol, disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut, atau alkohol saja, adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berawarna, dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa ini merupakan obat psikoaktif dan dapat ditemukan pada minuman beralkohol dan termometer modern. Etanol adalah salah satu obat rekreasi yang paling tua.
Dalam proses pengawetan mayat, orang Mesir kuno menggunakan berbagai macam campuran, termasuk di dalamnya metanol, yang mereka peroleh dari pirolisis kayu. Methanol murni, pertama kali berhasil diisolasi tahun 1661 oleh Robert Boyle, yang menamakannya spirit of box, karena ia menghasilkannya melalui distilasi kotak kayu. Nama itu kemudian lebih dikenal sebagai pyroxylic spirit (spiritus). Pada tahun 1834, ahli kimia Perancis Jean-Baptiste Dumas dan Eugene Peligot menentukan komposisi kimianya. Mereka juga memperkenalkan nama methylene untuk kimia organik, yang diambil dari bahasa Yunani methy = "anggur") + hŷlē = kayu (bagian dari pohon). Kata itu semula dimaksudkan untuk menyatakan "alkohol dari (bahan) kayu", tetapi mereka melakukan kesalahan.
Pada tahun 1923, ahli kimia Jerman, Matthias Pier, yang bekerja untuk BASF mengembangkan cara mengubah gas sintesis (syngas/campuran dari karbon dioksida and hidrogen) menjadi metanol. Proses ini menggunakan katalis zinc chromate (seng kromat), dan memerlukan kondisi ekstrim —tekanan sekitar 30–100 MPa (300–1000 atm), dan temperatur sekitar 400 °C. Produksi metanol modern telah lebih effisien dengan menggunakan katalis tembaga yang mampu beroperasi pada tekanan relatif lebih rendah.
2.1 Produksi Metanol dari bahan baku biomas
Biomas sebagai material organik atau biologis karena sebagian besar komposisinya mengandung atom karbon, hidrogen, oksigen maupun nitrogen dan dihasilkan oleh proses biologis, misalnya hasil pertanian, perkebunan, sampah organik, limbah cair pembuatan tahu, limbah padat dan cair penggilingan tebu, feses hewan ternak dan sebagainya. Pada prinsipnya biomas sudah mengandung energi potensial yang dapat diubah menjadi berbagai macam energi lain, misalnya energi panas. Hasil proses pembakaran biomas dapat dimanfaatkan untuk memanaskan air yang kemudian menghasilkan uap untuk menggerakkan turbin pembangkit tenaga listrik. Membakar biomass bukan salah satu cara terbaik menghasilkan energi panas karena dampak langsung yang dihasilkan dari pembakaran biomass tidak baik untuk lingkungan dan efisiensi energi yang dihasilkan tidaklah demikian besar akibat dari pembakaran tidak sempurna. Maka perlu dipikirkan cara untuk mendapatkan sumber energi yang efisien dengan cara mengolah biomas.
Gas methan atau biogas merupakan gas yang dihasilkan dari proses pembusukan material organik, methanol maupun ethanol dapat dihasilkan dari proses fermentasi produk pertanian yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi, misalnya jagung dan kentang. Sementara itu minyak yang dihasilkan dari segala macam bijian-bijian yang dapat dimakan, minyak kelapa maupun minyak tanaman jarak, tanaman sorgum, bahkan minyak jelantah dapat diubah menjadi bahan bakar mesin diesel dan disebut sebagai biodiesel.
Biomas tidak melulu digunakan sebagai material penghasil energi, namun dia juga dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku antara (intermediate) yang nantinya diubah menjadi material industri. Kita mengenal plastik merupakan hasil proses polimerisasi senyawa hidrokarbon dari minyak dan gas bumi. Gas methan, methanol dan ethanol yang dihasilkan dari biomass juga dapat diubah menjadi plastik melalui berbagai macam proses kimiawi (polimerisasi). Surfaktan untuk deterjen atau pelumas bisa dihasilkan dari minyak kelapa. Chitosan yang diekstrak dari limbah perikanan bisa diubah menjadi polimer yang dapat dimakan (edible polymer) atau bahkan sebagai polimer untuk proses industri, misalnya polimer membran untuk memisahkan berbagai macam gas. Biomass yang juga merupakan sumber bahan pangan pokok (feedstock), misalnya tepung jagung, bisa diubah menjadi material bernilai tambah (added value material) menjadi senyawa aditif dalam teknologi pangan, misalnya sorbitol (salah satu jenis gula diet). Lebih jauh lagi, limbah padat misalnya tandan kelapa sawit, ampas penggilingan tebu, atau serat enceng gondok dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan bahan bangunan (multipleks, panel, atau komposit serat-plastik). Sampah pangan dan produk pertanian bisa langsung dimanfaatkan sebagai material pembuatan kompos untuk pertanian organik, sebuah cara bercocok tani yang tidak menggunakan zat penyubur dan pembasmi hama sintetis.
Dari segala macam contoh sederhana di atas dengan sudut pandang pengembangan teknologi berwawasan ramah lingkungan, yang paling menarik dan menggugah minat industri besar adalah mengubah biomass menjadi material sumber energi dan senyawa kimia antara. Sedangkan mengubah biomass menjadi aditif bahan pangan, material pendukung pertanian atau material rumah tangga tampaknya lebih sesuai bagi kalangan industri kecil dan menengah.
Teknologi BTL (Biomass To Liquid) pada dasarnya terdiri atas dua proses, proses pencairan tidak langsung dimulai dengan reaksi reformasi/gasifikasi bahan baku menjadi gas sintesis (campuran gas hidrogen dan karbon monoksida), diikuti dengan sintesis Fischer-Tropsch (F-T) dari gas sintesis menghasilkan minyak sintesis (syncrude), dan upgrading minyak sintesis menjadi bahan bakar sintesis seperti diesel (solar) sintesis yang dikenal sebagai F-T diesel, liquefied petroleum gas (LPG), kerosin dan naftalen. F-T liquid memiliki keunggulan, yaitu hampir bebas dari kandungan sulfur (< 5 ppm), rendah kandungan aromatik (< 1 persen), biodegradable, tidak beracun, dapat digunakan tanpa modifikasi infrastruktur, dan memiliki emisi polutan yang rendah. Gambar di bawah ini menampilkan diagram alir sederhana teknologi BTL.
Gambar 1. Diagram alir proses konversi biomassa menjadi bahan bakar cair.
Dari diagram alir di atas, terlihat bahwa teknologi BTL ini dimulai dengan melakukan perlakuan awal terhadap biomassa yang digunakan sebagai umpan. Perlakuan awal ini mencakup pengecilan ukuran dan pengeringan yang dilakukan dalam sebuah rotary dryer. Panas yang diperlukan pada proses pengeringan ini diperoleh dari panas sensibel gas buang.
Bagian proses selanjutnya adalah proses gasifikasi biomassa. Gasifikasi biomassa adalah proses bertemperatur tinggi (600-1000°C) untuk mendekomposisi hidrokarbon dalam biomassa menjadi molekul-molekul gas yang terutama terdiri dari hidrogen, karbon monoksida, dan karbon dioksida. Pada banyak kasus, proses gasifikasi juga menghasilkan arang, tar, serta metanol, air, dan berbagai molekul dan senyawa lainnya. Konversi biomassa menjadi gas sintesis secara umum melibatkan dua proses. Proses pertama adalah pirolisis. Pirolisis melepaskan gas-gas terbang yang terkandung dalam biomassa pada temperatur di bawah 600°C melalui serangkaian reaksi yang kompleks. Proses berikutnya adalah konversi arang.
Banyak metode gasifikasi yang tersedia untuk memproduksi gas sintesis. Metode-metode ini akan menghasilkan komposisi gas sintesis yang beraneka-ragam yang mana variasi perbandingan CO dengan H2 dapat tercapai. Gas sintesis yang diproduksi oleh metode yang berbeda akan mengandung pengotor yang berbeda-beda. Pengotor ini selanjutnya akan mempengaruhi proses yang akan berlangsung dalam reaktor Fischer-Tropsch berkaitan dengan racun katalis sehingga diperlukan pencucian gas sintesis. Salah satu metode gasifikasi berskala komersial telah dikembangkan oleh CHOREN.
Gas sintesis yang dihasilkan dari proses gasifikasi mengandung kontaminan yang berbeda-beda seperti partikulat, tar, alkali, H2S, HCl, NH3, dan HCN. Kontaminan ini akan menurunkan aktivitas pada sintesis Fischer-Tropsch karena akan meracuni katalis. Sulfur adalah racun yang tidak dapat dihilangkan dari katalis yang mengandung kobalt dan besi karena sulfur akan melekat pada sisi aktif katalis. Selain sulfur, tar yang dihasilkan pada proses gasifikasi dapat menimbulkan kerak pada peralatan dan memasuki pori pada penyaring ketika terkondensasi. Untuk menghindari terjadinya hal-hal tersebut, tar harus berada di bawah titik embunnya pada tekanan operasi sintesis Fischer-Tropsch. Oleh karena itu, tar sebaiknya direngkah menjadi hidrokarbon dengan rantai yang lebih pendek.
Setelah mengalami gasifikasi, gas sintesis akan diproses dalam reaktor sintesis Fischer-Tropsch. Pada umumnya, katalis yang digunakan dalam proses ini adalah besi atau kobalt dengan silika sebagai support. Namun, kualitas gas sintesis hasil gasifikasi biomassa belum memenuhi persyaratan dilangsungkannya sintesis Fischer-Tropsch, karena itu perlu dilakukan pengkondisian terlebih dahulu. Gas sintesa hasil gasifikasi memiliki rasio H2/CO sekitar 0.6-0.8, sedangkan sintesis Fischer-Tropsch membutuhkan rasio tersebut sekitar 2. Karenanya, gas sintesa akan mengalami shift reaction untuk menambahkan H2 hingga memenuhi persyaratan berlangsungnya sintesis Fischer-Tropsch. Shift reaction berlangsung dengan mekanisme sebagai berikut:
CO + H2O -> CO2 + H2
Namun, penerapan teknologi ini membutuhkan biaya investasi yang sangat besar dengan pay back period sekitar 15-20 tahun. Perhitungan dilakukan berkaitan dengan feasibilitasnya untuk diterapkan di Indonesia, karenanya beberapa asumsi perhitungan juga disesuaikan dengan kondisi di Indonesia seperti bahan baku yang digunakan adalah tandan kosong sawit (TKS) dengan harga Rp 500,-/kg dan harga bahan bakar BTL ini sama dengan harga BBM di Indonesia tanpa subsidi (berarti sekitar Rp10.000 untuk bensin dan Rp8.000 untuk solar). Perhitungan dilakukan tanpa mempertimbangkan nilai suku bunga yang berlaku, karena pabrik tidak mengalami keuntungan jika suku bunga diterapkan.
2.2 Kandungan Metanol (RON) pada bahan bakar
Rata-rata Range oktan (RON) pada bensin dari 20 kota adalah 89,4, adapun range dari angka oktan tersebut adalah minimum 87,90 dan maksimum 91,70. Dapat dikatakan bahwa RON pada bensin jenis premium di Indonesia telah cukup baik. Berdasarkan hasil pemantauan, angka oktana cukup baik (di dasarkan pada spesifikasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Migas) terkecuali ada 1 contoh uji yang diambil dari salah satu SPBU di kota Semarang yang menunjukkan bilangan oktan tidak mencapai 88 tetapi hanya 87,90.
Untuk jenis solar, rata-rata kandungan belerang adalah 1.561 ppm dnegan range minimum 700 ppm sampai dengan maksimum 3.300 ppm. Ada beberapa kota yang mengalami kenaikan rata-rata belerang dalam bensin yaitu Jakarta, Batam, Palembang dan Yogyakarta, dan juga terjadi penurunan kadar belerang dalam solar yang cukup signifikan yaitu Bandung, Surabaya dan Makasar.
2.3 Campuran metanol
Kendala metanol dangan konsentrasi 15% ini adalah merupakan campuran yang akan memisah dalam waktu beberapa menit dikarenakan campuran yang kandungan metanol yang sedikit ini terdapat perbedaan berat jenis dengan campurannya. Paling tidak di sini metanol bersifat sebagai pelarut bersifat polar, namun dalam jumlah yang sedilit pada pelarutnya, hingga terjadi penggumpalan yang menyebabkan campurannya tidak homogen. Konsentrasi larutan menyatakan secara kuantitatif komposisi zat terlarut dan pelarut di dalam larutan.
2.4 Kendala metanol sebagai bahan bakar
Metanol sebagai bahan bakar ini bersifat bahan bakar tinggi ini bila dalam konsentrasi sebesar 15% dapat mengalami kendala yang salah satunya diakibatkan oleh campuran akan memisah dalam waktu beberapa menit saja. Hal ini dikarenakan oleh perbedaan konsentrasi.. Konsentrasi umumnya dinyatakan dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah total zat dalam larutan, atau dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah pelarut.
2.5 Bahan aditif pada metanol
Bahan additif adalah bahan yang dicamurkan pada senyawa tertentu untuk membantu proses untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Tidak dapat dimungkiri, kebutuhan aditif sebagai pendongkrak angka oktan yang dapat mempercepat laju kendaraan bermotor memang ada. Metanol, umumnya, digunakan sebagai bahan additif yang baku untuk berbagai macam produk petrokimia, sintesis kimia (misal: formaldehid, asam asetat, metil amina) dan bahan bakar mesin bakar internal pada kendaraan bermotor yang sudah dikenal sejak sekitar tahun 1960-an. Sekarang metanol akan mulai diterapkan sebagai bahan bakar kendaraan fuel cell. Secara ekonomi metanol mempunyai dampak yang cukup berarti terhadap perkembangan dunia karena dapat menyumbangkan pendapatan 12 milyar USD per tahun dan dapat menciptakan lebih dari 100.000 lapangan kerja.
2.6 Jarak yang dapat ditempuh
Dalam penggunaan bahan baku metanol ini, kita tidak bisa memprediksikan seberapa banyak jarak yang ditempuh dalam suatu mesin, karena terdapat kapasitas tertentu dari suatu mesin kendaraan bermotor tersebut bila belum ada praktiknya, namun menurut saya metanol bisa/layak dijadikan bahan bakar masa depan kerena memliliki angka oktan yang lebih tinggi dibanding bensin taraf premium.
2.7 Penggunaan metanol (manfaat dan kelemahan)
Metanol digunakan secara terbatas dalam mesin pembakaran dalam, dikarenakan methanol tidak mudah terbakar dibandingkan dengan bensin. Metanol campuran merupakan bahan bakar dalam model radio kontrol. Salah satu kelemahan metanol sebagai bahan bakar adalah sifat korosi terhadap beberapa logam, termasuk aluminium. Metanol, merupakan asam lemah, menyerang lapisan oksida yang biasanya melindungi aluminium dari korosi:
6 CH3OH + Al2O3 → 2 Al(OCH3)3 + 3 H2O
Ketika diproduksi dari kayu atau bahan oganik lainnya, metanol organik tersebut merupakan bahan bakar terbarui yang dapat menggantikan hidrokarbon. Namun mobil modern pun masih tidak bisa menggunakan BA100 (100% bioalkohol) sebagai bahan bakar tanpa modifikasi. Metanol juga digunakan sebagai solven dan sebagai antifreeze, dan fluida pencuci kaca depan mobil.
Api dari metanol biasanya tidak berwarna. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati bila berada dekat metanol yang terbakar untuk mencegah cedera akibat api yang tak terlihat. Dewasanya, hal ini menyebabkan metanol masih kurang mendapat perhatian daripada bahan bakar etanol. Bahan bakar direct-metanol unik karena suhunya yang rendah, operasi pada tekanan atmofser, mengijinkan mereka dibuat kecil. Ditambah lagi dengan penyimpanan dan penanganan yang mudah dan aman membuat metanol dapat digunakan dalam perlengkapan elektronik.
Penggunaan metanol sebagai bahan bakar mulai mendapat perhatian ketika krisis minyak tahun 1970-an karena ketersediaan, biaya rendah, dan manfaat lingkungan. Pada pertengahan 1990, lebih dari 20.000 "kendaraan bahan bakar fleksibel" (VCF) mampu berjalan pada metanol atau bensin yang dijual di Amerika Serikat. Selain itu, untuk bahan bakar bensin banyak 1980-an dan awal 1990, dijual di Eropa adalah campuran persentase kecil metanol. produsen mobil berhenti membangun VCFs metanol pada tahun 1990-an, mengalihkan perhatian mereka ke kendaraan didukung oleh etanol. Sedangkan program VCF untuk metanol sukses teknis, kenaikan harga methanol pada pertengahan hingga akhir tahun 1990 selama periode penurunan harga bensin jatuh bunga dalam metanol sebagai bahan bakar.
Perusahaan penghasil metanol di Indonesia diantaranya adalah Pertamina dan PT. Kaltim Methanol Industry (PT. KMI) dengan bahan baku gas alam. Pabrik metanol Pertamina berada di Pulau Bunyu dengan kapasitas produksi 110 juta galon/tahun sedangkan pabrik metanol PT. KMI berada di Kalimantan Timur dengan kapasitas produksi sekitar 220 juta galon/tahun. Produksi metanol dari Indonesia diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri antara 167.000 – 834.000 galon per bulan selebihnya dieksport ke Amerika , Korea , Jepang, dan Taiwan. Saat ini kapasitas produksi metanol dunia diperkirakan sekitar 12,5 milyar galon (37,5 juta ton) per tahun. Jika dilihat dari jumlah ini maka produksi metanol Indonesia hanya sekitar 2,67% dari produksi dunia.
Dari segala macam contoh sederhana di atas dengan sudut pandang pengembangan teknologi berwawasan ramah lingkungan, yang paling menarik dan menggugah minat industri besar adalah mengubah biomass menjadi material sumber energi dan senyawa kimia antara. Sedangkan mengubah biomass menjadi aditif bahan pangan, material pendukung pertanian atau material rumah tangga tampaknya lebih sesuai bagi kalangan industri kecil dan menengah.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan yang didapat dalam makalah di atas adalah:
1. Metanol dapat dibuat untuk bahan bakar spritus maupun kendaraan otomotif.
2. Metanol bersifat polar dan pelarut yang memiliki bilangan oktan lebih baik daripada bensin bertaraf premium.
3. Metanol diproduksi dari bahan baku biomas dengan proses pirolisis.
4. Metanol bisa menjanjikan sebagai bahan bakar sama halnya dengan etanol serta keadaannya lebih melimpah
5. Metanol dapat ditambahkan sebagai bahan additif untuk menyempurnakan kualitas bahan bakarnya.
6.
Dari makalah yang telah dibahas sebelumnya, saya memberikan sedikit saran bahwa sebaiknya Pertamina tetap memproduksi bahan bakar metanol sebagai bahan bakar alternatif dengan upaya memperkecil kerugian yang ada pada produksi metanol dengan cara berangsur-angsur demi kelancaran penggunaan bahan bakar. Selain itu generasi di masa datang tidak akan mendapatkan vonis “bahan bakar musnah”, jaga dan simpan seperlunya.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim1.
http://es.wikipedia.org/wiki/Metanol
diakses pada tanggal 2 Oktober 2010
Anonim2.
http://id.wikipedia.org/wiki/Metanol
diakses pada tanggal 2 Oktober 2010
Anonim3.
http://id.wikipedia.org/wiki/Pirolisis
diakses tanggal 6 Oktober 2010
Anonim4.
hhttp://green.kompasiana.com/group/limbah/2010/07/13/biomass-dan-sampah-organik-timbunan-emas-hijau-yang-mulai-dilirik-industri/
diakses pada tanggal 2 Oktober 2010
Anonim5.
http://majarimagazine.com/2008/05/biomass-to-liquid-btl/
diakses pada tanggal 2 Oktober 2010
Anonim6.
http://raydenmas.blogspot.com/2008/05/kandungan-bensin-dan-solar.html
diakses pada tanggal 5 Oktober 2010
Anonim7.
http://www.batan.go.id/mediakita/current/mediakita.php?group=Artikel%20Lepas&artikel=tk1&hlm=1
diakses pada tanggal 4 Oktober 2010
Anonim8.
http://www.indobiofuel.com/menu%20biodiesel%20artikel%2018.php
diakses pada tanggal 2 Oktober 2010
semoga manfaat
PERCOBAAN 1 KOEFISIEN VISKOSITAS
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Tujuan Percobaan
Tujuan dari percobaan ini adalah menentukan koefisien viskositas bermacam-macam cairan dengan menggunakan hukum stokes.
1.2 Latar Belakang
Viskositas suatu fluida merupakan kekentalan suatu fluida, yang merupakan indeks hambatan aliran cairan. Viskositas dapat diukur / ditentukan dengan mengukur laju alir cairan yang melalui tabung berbentuk silinder. Viskositas fluida / cairan dipengaruhi oleh jenis fluida serta suhu, untuk larutan, viskositasnya dipengaruhi oleh konsentrasi.
Pada dasarnya hambatan gerakan benda didalam fluida disebabkan oleh gaya gesekan antara bagian fluida. Pada umumnya pengukuran koefesien viskositas fluida, khususnya cairan adalah berdasarkan hambatan gerakan bendadidalam fluida. Penentuan viskositas dengan hukum stokes sangat sederhana hanya saja diperlukan kelereng dari bahan amat ringan.
Percobaan ini dilakukan untuk menentukan koefesien viskositas bermacam-macam cairan dengan menggunakan hukum stokes. Dengan mengetahui viskositas tersebut, maka kita dapat menghitung gaya yang terjadi.
BAB II
DASAR TEORI
Viskositas suatu cairan murni atau larutan merupakan indeks hambatan alir cairan. Viskositas dapat ditentukan dengan mengukur laju aliran cairan yang melalui tabung berbentuk silinder. Cara ini merupakan salah satu cara yang paling mudah dan dapat digunakan baik untuk cairan maupun gas (Bird, 1985).
Viskositas berkaitan dengan keadaan atau fase viskeus, yakni fase diantara padat dan cair yang terjadi sewaktu bahan padat menjadi lembek sebelum cair sewaktu dipanaskan. Tidak semua bahan bahan padat mengalami fase viskeus sebelum menjadi cair. Dalam fase viskeus mengalirnya bahan tidak leluasa seperti cairan, karena adanya hambatan diantara bagian-bagiannya atau diantara lapisan-lapisannya dalam gerakan alirannya (Soedojo, 2004).
Viskositas berkaitan dengan keadaan dan tak lain membicarakan masalah gesekan antara bagian-bagian atau lapisan-lapisan cairan atau fluida pada umunya, yang bergerak satu terhadap yang lain. Gesekan atau hambatan tersebut ditimbulkan oleh gaya tarik menarik antar molekul disatu lapisan dengan molekul-molekul di lapisan lain. Gaya interaktif itu terutama ialah gaya elektrostatika, yaitu gaya antara muatan-muatan listrik (Soedojo, 2004).
Aliran cairan dapat dikelompokkan dalam dua tipe. Yang pertama adalah aliran laminar atau aliran kental yang secara umum menggambarkan laju aliran kecil. Aliran yang lain adalah aliran turbilan yang menggambarkan laju aliran yang besar melalui pipa dengan diameter yang besar (Dogra & Dogra, 1990).
Gaya gesekan antara permukaan benda padat dengan fluida medium dimana benda itu bergerak akan sebanding dengan koefisien realtif gerak benda itu terhadap medium (Soedojo, 2004).
Pada dasarnya hambatan gerakan benda padat di dalam fluida disebabkan oleh gaya gesekan antara bagian fluida yang melekat ke permukaan benda dengan bagian-bagian fluida diebelahnya dimana gaya gesekan itu diberikan sebanding dengan koefisien fluida. Menurut stokes, gaya gesekan itu diberikan oleh apa yang disebut hukum stokes.
F = 6 r v … (1)
F = Gaya gesek
r = jari-jari bola
v = kecepatan gerak bola
= viskositas fluida (Soedojo, 2004).
Besarnya koefisien viskositas bergantung pada jenis dan suhu fluida; untuk larutan, besarnya koefisien viskositas bergantung pada konsentrasi larutan tersebut. Pada umumnya pengukuran koefisien viskositas fluida, khususnya cairan adalah berdasarkan hambatan gerakan benda di dalam benda. Misalnya dengan mengukur kecepatan berputarnya silinder pada sumbunya bila silinder itu dibenamkan di dalam cairan yang hendak ditentukan koefisien viskositasnya dan dengan menetapkan kelereng alumunium yang sedang jatuh bebas dalam cairan (Soedojo, 2004).
BAB III
METODOLOGI PERCOBAAN
3.1 Alat beserta fungsinya
Alat-alat yang digunakan adalah ;
1. Tabung Viskositas
Sebagai wadah untuk melakukan percobaan, dimana oli dan minyak yang akan diukur viskositasnya dimasukkan ke dalam tabung tersebut.
2. Gelas ukur berisi cairan digunakan untuk mengukur volume cairan.
3. Stopwatch, untuk menghitung waktu bola baja saat mulai dilepaskan sampai jatuh ke dasar tabung viscometer.
4. magnet dan Nilon untuk mengambil bola dari fluida.
5. Neraca Ohaus untuk menimbang gelas ukur, fluida dan bola baja.
6. Mikrometer sekrup untuk mengukur diameter bola baja.
7. Bola baja sebagai alat yang dimasukkan ke dalam fluida.
3.2 BAHAN
Bahan-bahan yng digunakan pada percobaan ini adalah minyak sebanyak 700 mL & oli sebanyak 600 mL.
3.3 Prosedur Percobaan
1. Bersihkan dan keringkan tabung viskometer.
2. Timbang bola besi dan gelas ukur kosong, lalu ukur diameter bola.
3. Masukkan zat cair kedalam gelas ukur dan timbang, catat volume dan massany alalu masukkan zat cair kedalam tabung viskometer
4. Masukkan bola besi kedalam tabung viskometer catat waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 80 cm, 70 cm, 60 cm, 50 cm dan 40 cm (jaga agar tidak ada gelembung udara yang ikut bersama bola pada saat masuk kedalam viskometer).
5. Mengulangi langkah no. 6 untuk bola besi dengan ukuran yang berbeda.
6. Mengulangi langkah no. 4, 5, 6 dan 7 untuk jenis cairan yang berbeda.
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Data hasi percobaan
No Keterangan Hasil
1. Massa bola 8,5 gr
2. Diameter bola 12,16 mm
3. V miyak 100 ml
4. Massa gelas ukur kosong 129 gr
5. Massa gelas ukur dan muyak 100 ml 218 gr
6. Tinggi kolom viskositas 80 cm
7. Suhu awal 32 oC
8. Pwngukuran kecepatan bola pada :
A. 32 oC
Waktu pengukuran : I 0,95 S
II 0,93 S
III 0,95 S
IV 0,91 S
V 0,93 S
B. 32 oC + 5 oC = 37 oC
Waktu pengukuran : I 0,86 S
II 0,85 S
III 0,86 S
IV 0,89 S
V 0,88 S
C. 32 oC + 10 oC = 42 oC
Waktu pengukuran : I 0,76 S
II 0,88 S
III 0,88 S
IV 0,86 S
V 0,84 S
D. 32 oC + 15 oC = 47 oC
Waktu pengukuran : I 0,86 S
II 0,73 S
III 0,84 S
IV 0,81 S
V 0,83 S
4.2 PEMBAHASAN
Pada percobaan ini dilakukan pengukuran harga viskositas dari suatu zat cair. Disimi digunakan tabung panjang yang memunyai prinsip yang sama dengan viskometer. Pada tabung ini diisi dengan zat cair yang akan diukur viskositasnya dengan cara menjatuhkan bola baja yang telah diketahui diameternya dan waktu yang diperlukan bola mencapai dasar tabung. Selain ukuran bola, tinggi dan volume cairan yang diisi tabung perlu diukur untuk dimasukkan dalam perhitungan untuk mengetahui harga viskositasnya.
Ukuran bola baja mempengaruhi cepat atau tidaknya waktu yang diperlukan untuk mencapai dasar tabung. Disini ukuran dan masa bola yang dipakai adalah 12,16 mm dan 8,5 gram. Setelah diperoleh waktu yang diperlukan oleh fluida tersebut dicatat, kemudian dipanaskan. Setelah dibandingkan waktu yang diperoleh lebih kecil (lebih cepat). Hal ini disebabkan pemanasan yang dilakukan akan menurunkan harga viskositas dari minyak / oli tersebut. Turunnya harga viskositas ini karena kerapatan dari partikel minya/oli berkurang karena pemanasan tersebut
Dari fluida yang dipakai, maka semakin kental (oli paling kental) maka bola yang dipai lebih berat dan besar ukurannya. Dari teori semakin besar suhu pemanasan pada fluida yang dipakai maka semakin kecil viskositasnya. Berdasarkan perhitungan didapat bahwa viskositas minyak lebih kecil pada viskositas oli. Pada oli viskositas ( ) yang diperoleh berkisar 12,09 poise, sedangkan viskositas ( ) pada minyak goreng berkisar antara 6,11 – 7,95 poise. Hal ini dibuktikan perbedaan pada percobaan. Dapat dilihat bola lebih lambat jatuh pada oli dari pada dalam minyak goreng.
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut
1. Bola baja lebihcepat jatuh pada minyak goring dibandingkan bola yag dijatuhkan pada oli
2. viskositas oli lebih besar daripada minyak goring
3. viskositas oli atau minyak akan turun apabila dilakukan pemanasan
4. Nilai viskositas oli berkisar antara 8,11-12,09 poise,pada minyak goreng berkisar 6,11-7,95 poise
5. Kecepaan jatuhnya bola dalam minyak goring adalah 81,21-105,26 cm/s,dan pada oli adalah sebesar 55-82 cm/s.
5.2 Saran
1. Pada saat percobaan hendaknya tidak ada gelembung yang terjadi pada cairan yang akan diuji viskositasnya.
2. Untuk cairan yang kental hendaknya digunakan bola yang massanya besar.
Daftar Pustaka
Bird, Tony. 1985. Kimia Fisika untuk Universitas. PT Gramedia. Jakarta.
Dogra, S:K. dan S.Dogra. 1990. Kimia Fisika dan soal-soal. UI press. Jakarta.
Soedojo, Peter. 2004. Fisika Dasar. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Sukardjo. 1997. Kimia Fisika. Penerbit Rineka Cipta. Yogyakarta.
Perhitungan
Diketahuia : T awal : 32,4 oC
R3 : 100
R4 : 1000
R2 : 30
Vcc : 2 V
Ditanya : 1. R1 4. Yn 7. 10. Xy
2. R2 5. x2 8 11. Kesalahan relatif
3. Xn 6. Xy 9. 12. Kesalahan relatif
13. Kesalahan relatif rata-rata
Jawab : 1. NB : x Vcc
:
: 1,818 V
VA : VB
VA : x Vcc
1,8 :
1,8 : 60
54 + 1,8 R1 : 60
R1 :
R1 : 3,33
2. RT : x R2
: x 30
: 3,33
3. X1 : T
: (40 – 32,4) oC : 7,6
X2 : T
: (44 – 32,4) oC : 12,6
X3 : T
: (50 – 32,4) oC : 17,6
X4 : T
: (55 – 32,4) oC : 22,6
X5 : T
: (60 – 32,4) oC : 27,6
X6 : T
: (65 – 32,4) oC : 32,6
X7 : T
: (70 – 32,4) oC : 37,6
X8 : T
: (75 – 32,4) oC : 42,6
No T (oC) V terbaik
1. 40 oC
2. 45 oC
3. 50 oC
4. 55 oC
5. 60 oC
6. 65 oC
7. 70 oC
8. 75 oC
RT : + R2
No T (oC) RT (hambatan thermostaf)
1. 40 oC x 30 = - 23,5254
2. 45 oC 2 - x 30 = - 24,156
3. 50 oC 2 - x 30 = - 25,238
4. 55 oC 2 - x 30 = - 25,909
5. 60 oC 2 - x 30 = - 27,317
6. 65 oC 2 - x 30 = - 28,0645
7. 70 oC 2 - x 30 = - 28,779
8. 75 oC 2 - x 30 = - 30,264
4. Yn :
No T (oC) Yn
1. 40 oC = - 8,0646
2. 45 oC = - 8,254
3. 50 oC = - 8,578
4. 55 oC = - 8,78
5. 60 oC = - 9,203
6. 65 oC = - 9,429
7. 70 oC = - 9,648
8. 75 oC = - 9,7879
No X Y X2 Xy
1. 7,6 - 8,0646 57,76 - 61,290896
2. 12,6 - 8,254 158,76 - 104,0004
3. 17,6 - 8,578 309,76 - 150,9728
4. 22,6 - 8,78 510,76 - 198,728
5. 27,6 - 9,203 761,76 - 254,0028
6. 32,6 - 9,429 1062,76 - 307,3202
7. 37,6 - 9,648 1413,76 - 362,7648
8. 42,6 - 9,7879 1814,76 - 416,96454
200,8 - 71,7415 6090,08 - 1855,7445
a. :
:
:
: - 0,052388
: - 0,05
b. :
:
:
: - 7,6528737
: - 7,65
No T / n (oC) Y persamaan : (a x n) +b
1. 40 oC (- 0,05 x 40) + (- 7,65) = - 9,65
2. 45 oC (- 0,05 x 45) + (- 7,65) = - 9,9
3. 50 oC (- 0,05 x 50) + (- 7,65) = - 10,15
4. 55 oC (- 0,05 x 55) + (- 7,65) = - 10,4
5. 60 oC (- 0,05 x 60) + (- 7,65) = - 10,65
6. 65 oC (- 0,05 x 65) + (- 7,65) = - 10,9
7. 70 oC (- 0,05 x 70) + (- 7,65) = - 11,15
8. 75 oC (- 0,05 x 75) + (- 7,65) = - 11,4
No
Keterangan Kesalahan relatif : x 100%
1. Y1 x 100 % = 16,429 %
2. Y2 x 100 % = 16,626 %
3. Y3 x 100 % = 15,4876 %
4. Y4 x 100 % = 15,5769 %
5. Y5 x 100 % = 13,586 %
6. Y6 x 100 % = 13,513 %
7. Y7 x 100 % = 13,7798 %
8. Y8 x 100 % = 14,14 %
kesalahan relatif : 16,429 % + 16,626 % + 15,4876 % + 15,5769 % + 13,586 % + 13,513 % + 13,7798 % + 14,14 %
: 119,1383 %
Kesalahan relatif rata-rata :
:
: 14,89 %
semoga manfaat
PERCOBAAN 2 TEGANGAN PERMUKAAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Tujuan Percobaan
Tujuan percobaan ini adalah menentukan tegangan permukaan plat gelas dan cincin newton pada air, larutan garam dan larutan sabun.
1.2. Latar Belakang
Tegangan permukaan suatu zat cair terjadi karena perbedaan resultan gaya tarik molekul yang berada di permukaan zat cair tersebut. Tegangan permukaan cairan banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya: pada penggunaan detergen. Dalam bidang teknik kimia tegangan permukaan berpengaruh pada proses penyaringan dan pemisahan bahan-bahan cair.
BAB II
DASAR TEORI
Mungkin kita pernah mengamati seekor nyamuk terapung di permukaan air atau barangkali, kita pernah mengapungkan sebuah pisau silet atau sebuah jarum jahit di atas permukaan air. Jika diletakkan dengan hati-hati, pisau silet dan jarum jahit bisa terapung dipermukaan, walaupun menurut hukum archimedes, keduanya harus tenggelam karena massa jenis keduannya lebih besar dari massa jenis air. Gejala yang menahan nyamuk, pisau silet dan jarum sehingga bisa terapung dipermukaan air disebut dengan tegangan permukaan pada fluida (Foster,2003).
Molekul-molekul didalam suatu fluida akan selalu mengalami gaya tarik-menarik dengan molekul-molekul sejenis lainnya. Gejala ini disebut dengan gaya kohesi. Namun, molekul-molekul yang berada pada permukaan atau sangat dekat dengan permukaan lebih banyak mengalami gaya ke bawah dibandingkan gaya menarik ke atas (Foster, 2003).
Molekul–molekul cairan bagian dalam ditarik oleh molekul–molekul lain kesegala arah, tetapi molekul–molekul pada permukaan cairan hanya ditarik kearah dalam. Akibat dari hal ini, cairan selalu ingin memiliki permukaan terkecil atau cairan selalu ingin mengkerut. Misalnya tetesan cairan selalu berbentuk bulat. Berhubung dengan hal ini, bila permukaan cairan diperluas, ada gaya yang menahan, seakan – akan permukaan cairan mempunyai tegangan. Gaya tarik menarik antara molekul – molekul yang sejenis disebut kohesi, sedangkan gaya tarik antara molekul yang tidak sejenis disebut adhesi. Molekul – molekul air dan gelas mempunyai adhesi yang besar, hingga air dapat membasahi gelas. Sebaliknya, adhesi antara air raksa dan gelas kecil sekali, hingga air raksa tidak membasahi gelas ( Sukardjo, 1990 ).
Molekul – molekul zat cair memberikan gaya tarik satu sama lain. Gaya tarik ini bekerja pada molekul kedua yang berada jauh di dalam zat cair dan pada molekul kedua di permukaan. Molekul di dalam zat cair berada dalam kesetimbangan karena gaya – gaya molekul lain yang bekerja ke semua arah. Molekul di permukaan normalnya juga dalam kesetimbangan ( zat cair tersebut diam ). Hal ini benar walaupun gaya pada molekul di permukaan dapat diberikan hanya oleh molekul – molekul di bawahnya ( atau disampingnya ). Dengan demikian adanya gaya tarik total ke bawah, yang cenderung menekan lapisan permukaan sedikit tetapi hanya sampai batas dimana gaya ke bawah ini di imbangi oleh gaya ( tolak ) keatas yang disebabkan oleh kontak yang dekat atau tumbukan dengan molekul – molekul di bawahnya. Penekan permukaan ini berarti bahwa, intinya, zat cair meminimalkan garis permukaannya. Inilah sebab mengapa air cenderung membentuk tetesan berbentuk bola, karena sebuah bola mempresentasikan luas permukaan minimum untuk volume tertentu ( Giancoli, 2001 ).
Metode yang paling umum untuk mengukur tegangan permukaan adalah kenaikan atau penurunan cairan dalam pipa kapiler, yaitu :
=
Untuk menghitung besarnya tegangan permukaan ini, misalnya sebuah kawat kecil yang panjangnya L terapung dipermukaan zat cair. Jika gaya yang tegak lurus terhadap kawat ini dan terletak dipermukaan zat cair adalah F, maka tegangan permukaan didefinisikan sebagai :
=
Jika kita pandang suatu garis pada permukaan zat cair, maka bagian zat cair pada sebelah dari garis ini menarik bagian lain dari garis sebelah lain. Terikan ini adalah dalam bidang permukaan, dan tegak lurus garis tersebut (Sutrisno, 1999)
Sabun dan detergen mempunyai efek menurunkan tegangan permukaan air. Hal ini diinginkan untuk mencuci dan membersihkan karena tegangan permukaan air murni yang tinggi mencegahnya masuk dan dengan mudah diantara serat – serat materi dan lekuk – lekuk yang terkecil. Zat – zat yang memperkecil tegangan permukaan cairan disebut Surfactant (Giancoli, 2000).
Tegangan permukaan sebuah campuran zat cair bukan fungsi sederhana tegangan permukaan komponen murni karena komposisi cairan pada campuran tidak sama dengan komposisi pada badan cairnya. Ketika temperatur dinaikkan, tegangan permukaan zat cair dalam keadaaan setimbang dengan penurunan kerapatan uapnya dan mejadi nol pada titik kritis (Reid, 1991).
BAB III
METODOLOGI PERCOBAAN
3.1. Alat dan Fungsi Alat
Alat – alat yang digunakan pada percobaan :
1. Neraca torsi sederhana : sebagai pengukur massa
2. Neraca ohauss : untuk menimbang massa bahan yang digunakan
3. Pelat gelas dan cincin newton : sebagai alat untuk menetapkan tegangan permukaan, kedua benda ini dimasukkan ke dalam cairan yang diselidiki.
4. Jangka sorong : untuk mengukur panjang plat gelas.
5. Mikrometer skrup : untuk mengukur tebal plat gelas dan diameter cincin newton.
6. Bejana : untuk tempat cairan.
7. Batu timbangan : untuk menentukan massa tegangan berdasarkan skala pada neraca torsi.
3.2. Bahan yang Digunakan
Bahan yang digunakan adalah air, garam dan detergen sebanyak 100 gram.
3.3. Prosedur Kerja
1. Mengukur panjang dan ketebalan plat gelas dan cincin newton
2. Memasang plat gelas pada rangka kawat pada neraca torsi
3. Mengatur neraca supaya seimbang
4. Menempatkan beker gelas yang berisi air di bawah plat gelas. Merendam plat gelas ke dalam air perlahan-lahan menurunkannya. Mengamati kedudukan jarum neraca sesaat sebelum selaput pecah
5. Meminggirkan bejana air. Meletakkan batu timbangan pada pinggan nerca hingga jarum neraca tepat menunjukkan skala yang sama dengan no. 4. Mencatat berat batu timbangan.
6. Mengulangi percobaan untuk cincin newton
7. Mengulangi percobaan dengan larutan encer dan padat
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Percobaan
Hasil pengamatan
A. Diameter cincin Newton = 5,83 cm
B. Panjang plat gelas = 6,55 cm
C. Tebal plat gelas = 0,2 cm
Tabel 4.1.Plat gelas pada air biasa
No Skala pada neraca torsi Massa (gr)
1
2
3
4
5 2,6
3
3
3,2
3,8 1,1
1,3
1,3
1,4
1,6
Tabel 4.2 Cincin Newton pada air sabun
No. Kadar sabun (gr) Skala pada torsi Massa ( gr )
1.
2.
3.
4.
5. 5
10
15
20
25 3,2
3,4
3,6
3,8
4 1,3
1,4
1,5
1,6
1,8
Tabel 4.2 Cincin Newton pada air garam
No. Kadar garam (gr) Skala pada torsi Massa ( gr )
1.
2. 5
10 4
6 1,7
2,4
4.2 Pembahasan
Percobaan ini hanya menentukan tegangan permukaan dalam air biasa dengan menggunakan plat kaca, cincin Newton pada air sabun dan air garam. Sedangkan plat kaca pada air sabun dan air garam tidak dilakukan karena waktu yang tidak memungkinkan.
Dari hasil percobaan diperoleh data yang beragam, hal ini mungkin terjadi karena kurang telitinya membaca skala pada neraca atau angin yang dapat menyebabkan cepatnya selaput menjadi pecah atau karena masih adanya busa sabun yang ada di bejana sehingga data yang diperoleh kurang akurat.
Hasil perhitungan berdasarkan percobaan yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut. Pada percobaan menggunakan plat gelas pada air biasa dilakukan lima kali. Bila massanya besar, maka gaya yang ditimbulkan juga besar dan tegangan permukaannya pun besar.
Pada pada percobaan berikutnya yaitu menggunakan air sabun, tegangan permukaan dan gaya yang ditimbulkan menunjukan hal yang sama seperti pada air biasa. Jika semakin besar massa maka tegangan permukaaan dan gayapun semakin besar. Namun bila dibandingkan antara tegangan permukaan plat gelas pada air biasa dan air sabun dan air biasa, maka pada air sabun tegangan permukaannya lebih kecil, walaupun selaput sangat tipis, namun tebalnya masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran suatu molekul. Jadi masih dapat dianggap sebagai bagian dari zat cair yaitu suatu keseluruhan yang dibatasi oleh dua lapis permukaan yang tebalnya beberapa molekul.
Tegangan permukaan pada air garampun lebih kecil dari pada tegangan permukaan pada air biasa. Air garam mempunyai perbedaan nilai tegangan permukaan yang sangat besar ketika melakukan percobaan yang pertama dan yang kedua kali. Bahkan ketika melakukan percobaan yang ketiga, skala yang didapatkan adalah sangat besar yaitu lebih dari 6, sehungga tidak dapat dilakukan perhitungan massanya. Hal tersebut mungkin dikarenakan partikel-partikel yang terdapat pada air garam mempunyai gaya tarik yang cukup besar. Selain jenis cairan, temperatur juga mempunyai pengaruh yang cukup besar pada tegangan permukaan. Bila temperatur dinaikkan maka tegangan permukaan akan turun, begitu juga sebaliknya.
Bila kita lihat dari data hasil tegangan permukaan, maka terdapat perbedaan nilai untuk penggunaan plat kaca dan cincin Newton. Nilai tegangan permukaan dengan menggunakan cincin Newton lebih kecil dari plat kaca.
Hal-hal yang mempengaruhi tegangan permukaan adalah temperatur, massa jenis larutan dan keadaan- keadaan lain seperti angin.
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari beberapa percobaan yang telah dilakukan, maka didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Tegangan permukaan dari air biasa lebih besar daripada tegangan permukaan pada air sabun dan air garam.
2. Tegangan permukaan dipengaruhi oleh gaya yang terdapat dipermukaan cairan, jenis cairan, temperatur dan kondisi lain seperti angin.
3. Besar tegangan permukaan yaitu :
- Plat gelas pada air biasa yaitu 82,29 dyne/cm; 97,25 dyne/cm; 97,29 dyne/cm; 104,73 dyne/cm; dan 119,69 dyne/cm.
- Cincin newton pada air sabun yaitu 34,80 dyne/cm; 37,47 dyne/cm; 40,15 dyne/cm; 42,29 dyne/cm; dan 48,18 dyne/cm.
- Cincin newton pada air garam yaitu 45,50 dyne/cm; dan 64,24 dyne/cm.
5.2 Saran
Beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:
1. Persiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan sebelum praktikum dimulai.
2. Ketika membaca neraca torsi, pastikan bahwa kedudukan jarum neraca tepat pada saat sebelum selaput pecah, agar bisa mendapatkan hasil yang benar-benar akurat.
DAFTAR PUSTAKA
Foster , Bob, 2003, “Terpadu fisika”, Erlangga, Jakarta.
Giancoli, Douglas.C, 2001, “Fisika Jilid I”, Erlangga, Jakarta.
Reid, Robert.C, dkk, 1991, “Sifat Gas dan Zat Cair Edisi Ketiga”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Sutrisno, 1999, “Seri fisika, Fisika Dasar”, ITB, Bandung.
Perhitungan
1. menghitung tegangan permukaan
contoh perhitungan
* plat gelas pada air biasa
Dik : m = 1,1 gr
g = 980 cm/s2
l = 6,55 cm
Dit : F dan …?
Jawab : F = m . g
= 1,1 . 980
= 1.078 dyne
=
=
= 82,29 dyne/cm
*cincin newton pada air sabun
Dik : m = 1,3 gr
g = 980 cm/s2
r = 2,915 cm
Dit : F dan …?
Jawab : F = m . g
= 1,3 . 980
= 1.274 dyne
=
=
= 34,80 dyne/cm
*cincin newton pada air garam
Dik : m = 1,7gr
g = 980 cm/s2
r = 2,915 cm
Dit : F dan …?
Jawab : F = m . g
= 1,7. 980
= 1.666 dyne
=
=
= 45,50 dyne/cm
1. Tabel hasil perhitunga
Tabel 1. Plat kaca pada air biasa
No Panjang (cm) Massa (gr) F (dyne) g ( dyne/cm)
1
2
3
4
5 6,55
6,55
6,55
6,55
6,55 1,1
1,3
1,3
1,4
1,6 1078
1274
1272
1372
1568 82,29
97,25
97,25
104,73
119,69
Tabel 2. Plat kaca pada air sabun
No Jari-jari (cm) Kadar (gr) Massa (gr) F (dyne) g ( dyne/cm)
1
2
3
4
5 2,915
2,915
2,915
2,915
2,915 5
10
15
20
25 1,3
1,4
1,5
1,6
1,8 1274
1372
1470
1568
1764 34,80
34,47
40,15
42,99
48,18
Tabel 1. Plat kaca pada air biasa
No Jari-jari (cm) Kadar (gr) Massa (gr) F (dyne) g ( dyne/cm)
1
2
2,915
2,915
5
10
1,7
2,4
1666
2352
45,50
64,24
2. Sesatan
*menghitung sesatan pada plat gelas dalam air biasa
Dik : ∆m = 0,05
∆l = 0,005
l = 6,55 cm
g = 980 cm/s2
F = 1078 dyne
g = 82,29 dyne/cm
Dit : ∆g (sesatan)….?
Jawab : ∆g = x x g
= x x 82,29
= 3,766 dyne/cm
*menghitung sesatan pada plat gelas dalam air sabun
Dik : ∆m = 0,05
∆l = 0,005
r = 2,915 cm
g = 980 cm/s2
F = 1274 dyne
g = 34,80 dyne/cm
Dit : ∆g (sesatan)….?
Jawab : ∆g = x x g
= x x 34,80
= 1,33 dyne/cm
*menghitung sesatan pada plat gelas dalam air garam
Dik : ∆m = 0,05
∆l = 0,005
r = 2,915 cm
g = 980 cm/s2
F = 1666 dyne
g = 45,50 dyne/cm
Dit : ∆g (sesatan)….?
Jawab : ∆g = x x g
= x x 45,50
= 1,33 dyne/cm
3. Tabel perhitungan sesatan
Tabel 4. plat kaca pada air biasa
No l m ∆l ∆m g ∆ g
1 6,55 1,1 0,005 0,05 82,29 3,766
2 6,55 1,3 0,005 0,05 97,25 3,769
3 6,55 1,3 0,005 0,05 97,25 3,769
4 6,55 1,4 0,005 0,05 104,73 3,85
5 6,55 1,6 0,005 0,05 119,69 3,80
Tabel 4. plat kaca pada air sabun
No l m ∆l ∆m g ∆ g
1 2,915 1,3 0,005 0,05 34,80 1,33
2 2,915 1,4 0,005 0,05 37,74 1,36
3 2,915 1,5 0,005 0,05 40,15 1,34
4 2,915 1,6 0,005 0,05 42,99 1,36
5 2,915 1,8 0,005 0,05 48,18 1,32
Tabel 4. plat kaca pada air garam
No l m ∆l ∆m g ∆ g
1 2,915 1,7 0,005 0,05 45,50 1,33
2 2,915 2,4 0,005 0,05 62,24 0,97
semoga manfaat





